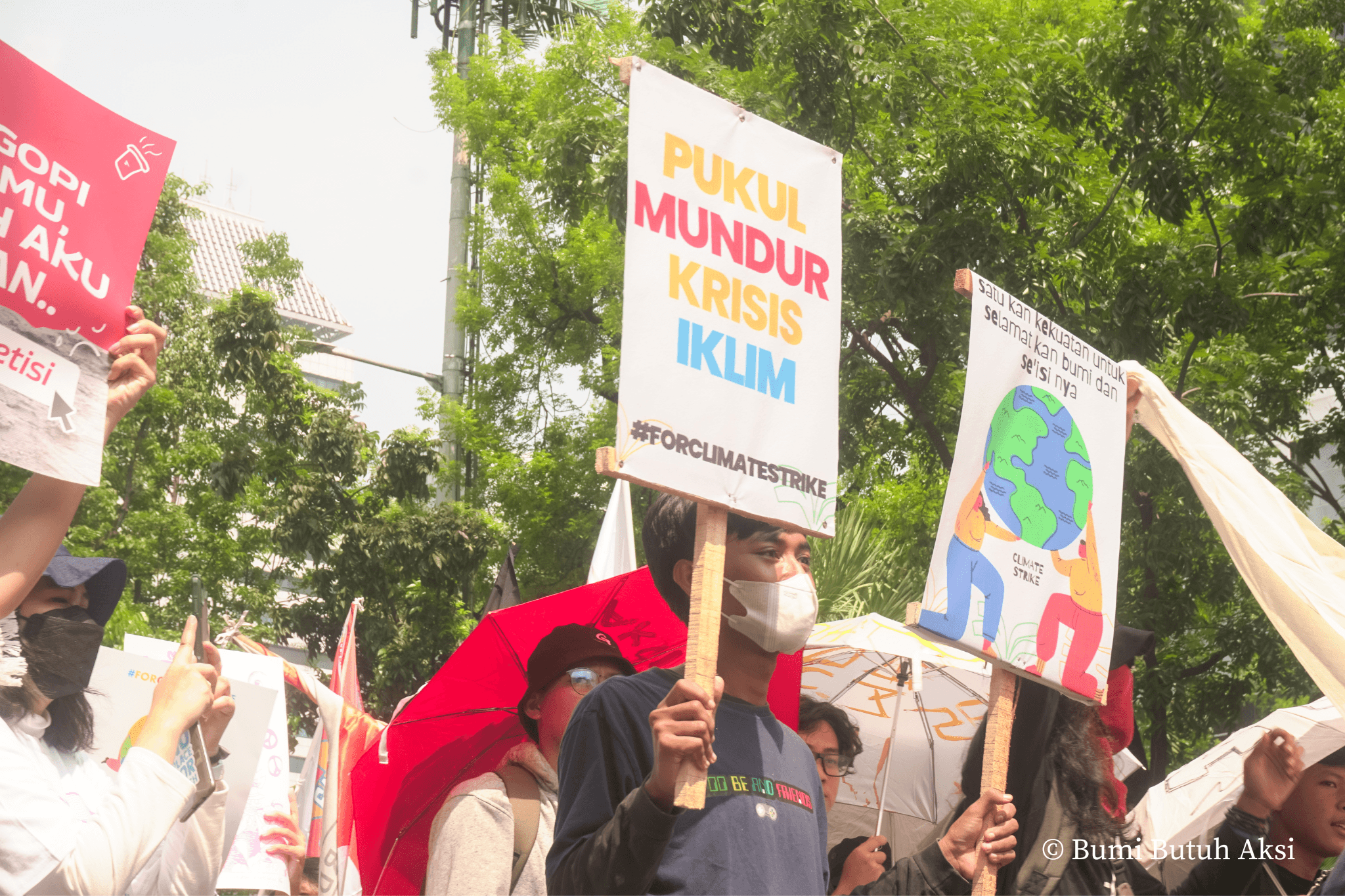Lima Kontradiksi Rencana Kelistrikan era Prabowo Subianto
Cintya Faliana • Penulis
09 Juli 2025
76
• 5 Menit membaca

Kredit foto: Presidenri.go.id
Presiden Prabowo Subianto berambisi membangun infrastruktur energi terbarukan berkapasitas 75 gigawatt (GW) dalam 15 tahun ke depan. Sayangnya, ambisi tersebut tidak diwujudkan dalam regulasi-regulasi penopang yang dapat menjadi landasan transisi energi.
Misalnya, peta jalan transisi energi yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih bergantung pada solusi palsu seperti teknologi penangkapan karbon. Lebih jauh, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034 yang diklaim sebagai RUPTL paling ‘hijau’ nyatanya masih menuai banyak kontradiksi dengan ambisi transisi energi.
Greenpeace mengungkapkan lima kontradiksi yang muncul dari RUPTL terbaru.
Pertama, dokumen yang dikeluarkan oleh PLN tersebut mencantumkan penambahan 76% PLTU batu bara dalam lima tahun pertama. PLN berdalih penambahan PLTU berkapasitas 6,3 GW dilakukan karena sumber energi fosil masih dianggap paling murah.
Jika pemerintahan Prabowo ‘memaksakan’ penambahan pembangkit energi fosil, cita-cita pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 akan sulit tercapai. Pasalnya, pemerintah terlanjur dalam posisi infrastructure lock-in atau terjebak pada satu jenis teknologi atau sumber daya tertentu dalam jangka panjang, meskipun ada pilihan yang lebih baik secara ekonomi, sosial, atau lingkungan.
Sementara, 72% penambahan energi terbarukan justru baru akan terjadi di periode kedua atau lima tahun berikutnya. Artinya, beban pembangunan energi terbarukan justru ditanggung oleh periode pemerintahan berikutnya, mengingat masa bertugas Presiden Prabowo hanya sampai 2029 saja.
Padahal, jika dilihat dari rentang waktu yang dibutuhkan, pembangunan pembangkit energi terbarukan sebenarnya lebih singkat dibandingkan PLTU. Misalnya, pembangkit listrik tenaga surya yang terbesar se-Asia Tenggara di Cirata, Jawa Barat, hanya dibangun dalam waktu tak sampai tiga tahun. Sementara ladang energi angin di Sulawesi Selatan hanya 2,5 tahun.
Kedua, riset IEEFA menunjukkan kapasitas listrik nasional naik sebesar 21 GW sepanjang 2018-2023. Namun, dominasi energi fosil masih sangat besar hingga mencapai 18,4 GW, sementara energi terbarukan hanya 3,2 GW saja.
Angka ini menunjukkan ketimpangan yang sangat besar dan membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengejar ketertinggalan di sektor energi terbarukan. Di sisi lain, dokumen RUPTL 2025-2034 justru masih melanjutkan ambisi pembangunan PLTU dan dominasi energi fosil.
Padahal, akibat lambatnya laju pengembangan proyek energi terbarukan, daya tarik investasi di sektor energi terbarukan pun semakin menurun. Situasi ini diperburuk oleh penurunan target energi terbarukan dari 23% menjadi 17-19% pada 2025 dan dari 26% menjadi 19-21% pada 2030.
Ketiga, sepanjang 2018-2023, kecepatan pembangunan energi terbarukan dalam negeri hanya 550 MW saja tiap tahunnya. Jika ingin mengejar target bauran energi terbarukan sekaligus pertumbuhan ekonomi 8%, pemerintahan Prabowo harus meningkatkan kecepatan ini hingga 4,4 kali lipat.
Namun, jika pemerintah berkukuh melakukan pembangunan energi terbarukan setelah 2029, maka peningkatan yang harus dilakukan mencapai 11 kali lipat dari kecepatan saat ini.
Sedangkan, proses pengadaan yang dilakukan PLN untuk proyek energi terbarukan masih rumit dan tidak transparan. Riset berjudul “The country of perpetual potential: Why is it so difficult to procure renewable energy in Indonesia?” mengungkapkan berbagai persoalan pengadaan yang dilakukan oleh PLN. Mulai dari volume pengadaan yang tidak memadai, kebijakan harga yang tidak menarik, hingga proses pengadaan yang tidak transparan. Belum lagi proses yang tidak efisien menurunkan kepercayaan investor.
PLN, sebagai satu-satunya pembeli dan pelaksana pengadaan, memiliki potensi konflik kepentingan karena juga berperan sebagai produsen listrik. Apabila PLN tidak berbenah, ekspansi menuju energi terbarukan akan semakin lambat dan jauh dari target yang ditetapkan.
Keempat, PLN justru berencana menambah kapasitas pembangkit listrik berbahan bakar gas fosil sebesar 10,3 GW periode 2025-2034. Padahal, gas adalah penyumbang emisi terbesar kedua setelah CO₂. Selain itu, gas juga mengandung metana yang justru mendorong pemanasan global 86 kali lebih tinggi dibandingkan CO₂.
Jika ingin memenuhi target Perjanjian Paris untuk menahan kenaikan suhu bumi maksimal 1,5°C, emisi metana harus dikurangi hingga 75%. Hal ini berbanding terbalik dengan penambahan pembangkit gas fosil menjadi 22 GW pada 2040 mendatang.
Pembangkit gas juga memiliki potensi kebocoran metana yang besar. Sementara, untuk mengurangi risiko kebocoran, negara pun harus menyiapkan biaya paling murah sebesar US$ 100 miliar (Rp1.500 triliun) dalam lima tahun ke depan. Angka ini mencakup belanja untuk teknologi deteksi kebocoran, program perbaikan, dan peningkatan peralatan yang bocor.
Terakhir, tingginya rencana penambahan pembangkit gas juga bisa berlawanan dengan target swasembada energi yang digaungkan Presiden Prabowo. Saat ini, pemerintah saja sedang ‘menghemat’ penggunaan gas karena pasokan yang belum mencukupi. Salah satunya disebabkan produksi gas yang konsisten menurun pada dekade terakhir. Jika pengembangan pembangkit gas mengacu pada RUPTL, Indonesia berisiko menjadi negara pengimpor gas (net gas importer) pada 2040.
Ketergantungan ini juga berisiko menyebabkan ketidakpastian biaya karena harga gas fosil yang fluktuatif di pasar global. Salah satu contohnya adalah ketika perang Rusia-Ukraina memicu krisis gas fosil global. Tingginya permintaan di tengah pasokan yang tersendat menyebabkan lonjakan harga gas hingga 1.900% dari titik terendah selama pandemi.
Rencana memperluas penggunaan gas sebagai bahan bakar transisi sama saja dengan menjebak negara dalam situasi gas lock-in. Jalur ini tidak hanya akan membahayakan kemajuan menuju target Net Zero Emissions pada 2060, tetapi juga melemahkan ketahanan energi serta memberikan dampak buruk pada lingkungan.
Belajar dari pengalaman masa lalu sebagai negara yang sempat menjadi pengekspor minyak, kini Indonesia justru menghabiskan triliunan rupiah untuk subsidi konsumsi minyak dalam negeri. Pemerintah perlu berhati-hati memutuskan langkah strategisnya agar tidak menjadi “keledai” dan jatuh ke lubang yang sama dua kali.