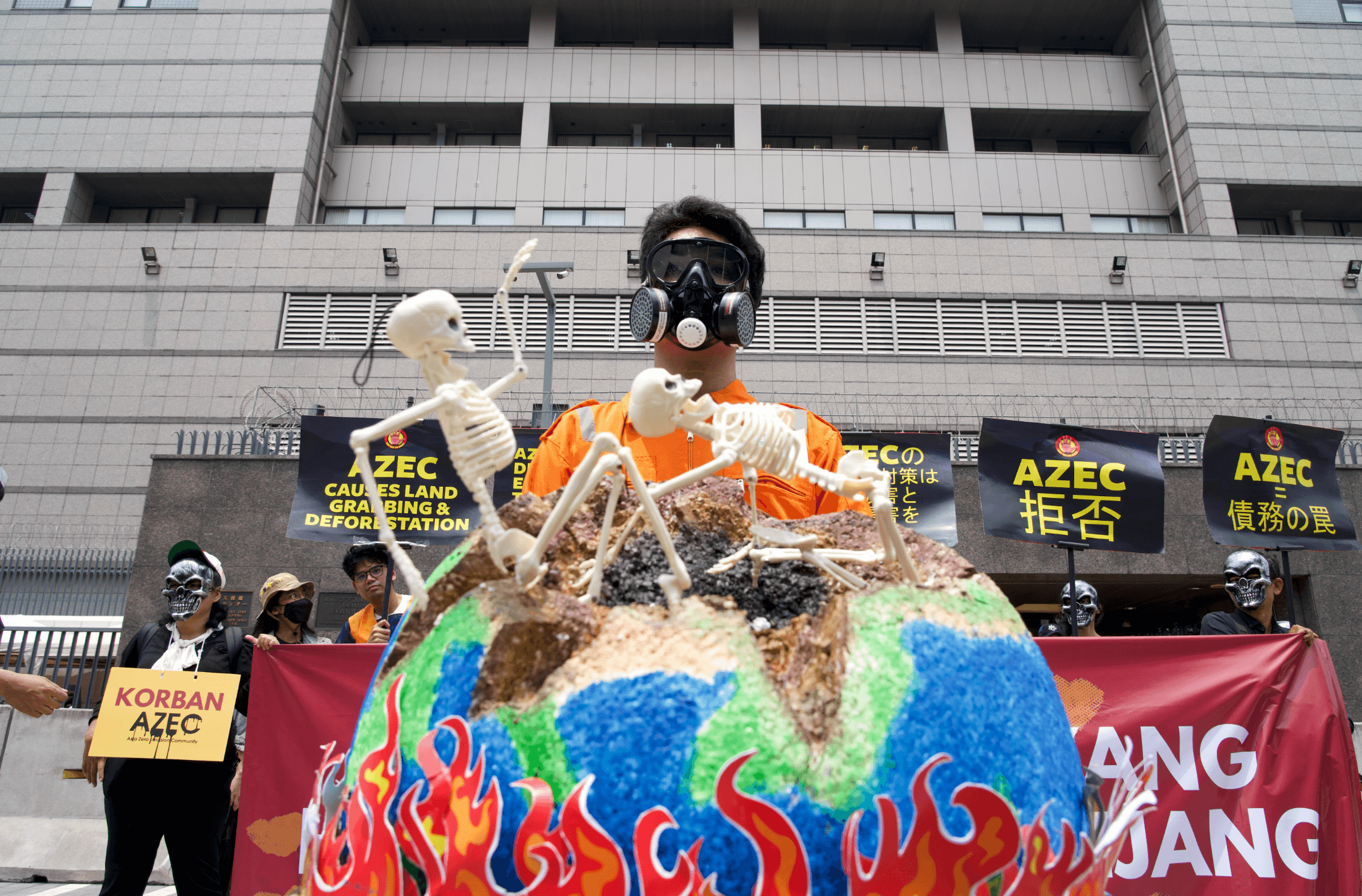Gasifikasi Batu Bara: Investasi Salah Arah Danantara
Sita Mellia • Penulis
17 Maret 2025
477
• 6 Menit membaca

Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kembali proyek gasifikasi batu bara untuk memproduksi dimethyl ether (DME) yang akan menggantikan Liquified Petroleum Gas (LPG) agar Indonesia tidak lagi mengimpor LPG. Pemerintah bahkan akan menggantikan 12% konsumsi LPG dengan DME mulai tahun 2025 hingga 2030, berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional.
Pemerintah seharusnya tak lagi memulai proyek ini pasca hengkangnya investor AS (Air Products and Chemicals Inc) dari proyek gasifikasi batu bara bersama PT. Bukit Asam Tbk. Proyek gasifikasi di Muara Enim, Sumatra Selatan ini tidak berlanjut sejak 2023 karena dinilai tidak ekonomis, bahkan diprediksi bakal merugi. Masalah lingkungan juga menghantui proyek ini.
Untuk menjalankan proyek gasifikasi, pemerintah kemungkinan besar akan menugaskan Danantara. Badan pengelola investasi ini rencananya menggelontorkan US$ 11 miliar atau Rp180 triliun—terbesar di antara proyek hilirisasi lainnya—untuk mendanai empat proyek gasifikasi batu bara.
Seberapa ekonomis DME menggantikan LPG?
Analisis dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) pada 2020 menunjukkan, biaya produksi DME dapat menyentuh US$ 470 (Rp 7,7 juta dengan kurs Rp 16.377) per ton, hampir dua kali lipat dibandingkan harga LPG yang sebesar US$ 365 per ton (Rp5,9 juta).
Pertamina, sebagai pembeli DME, selayaknya menginginkan harga DME yang lebih terjangkau dibanding mengimpor LPG. Namun, analisis IEEFA (2022) lagi lagi menunjukkan bahwa harga DME akan lebih murah hanya ketika harga impor LPG menyentuh US$858/ton (Rp 14 juta per ton) atau lebih tinggi. Harga ini hanya pernah terjadi 15 bulan dalam 20 tahun atau 6% dalam periode 2002 hingga 2021.
Biaya produksi DME akan menjadi lebih mahal lagi apabila pemerintah merealisasikan pemasangan CCS (carbon capture storage) atau teknologi penangkap karbon di proyek gasifikasi batu bara untuk menekan emisi gas rumah kaca. Proyek yang melepas 3 juta ton CO₂ per tahun ini memakan biaya penyimpanan karbon mencapai US$ 50-55 per ton CO₂, dan total investasi injeksi mencapai US$1,6 miliar.
Selain biaya produksi DME yang tinggi, proyek gasifikasi batu bara juga masih harus menanggung bunga pinjaman, mengingat kebutuhan investasi US$2 miliar kala itu rencananya didanai sepenuhnya dengan utang. Bunga sebesar 3,8% per tahun itu setara dengan biaya US$76 juta.
Beban biaya produksi tinggi dan bunga tersebut akan mendorong proyek gasifikasi batu bara merugi hingga Rp6,17 triliun per tahun, berdasarkan hitungan IEEFA. Hal ini karena DME tidak kompetitif dibandingkan dengan LPG di pasar global.
Sekalipun proyek ini dapat mengurangi impor LPG sebesar 980 ribu ton per tahun, pemerintah hanya menghemat sebesar Rp 5,86 triliun—masih kurang Rp 311,16 miliar untuk menutup total kerugian operasional

Perbandingan karakteristik LPG dan DME. Sumber: ESDM
Selain beratnya biaya produksi, penggunaan DME berpotensi lebih menguras dompet warga dibanding LPG. Hal ini dikarenakan DME memiliki heating value atau nilai kalor yang lebih rendah, yakni 7,749 kcal/kg. Sementara LPG bernilai kalor 12,076 kcal/kg.
Artinya, jika rumah tangga biasa menggunakan 1 kg LPG, mereka perlu menggunakan sekitar 1,6 kg DME untuk mendapatkan panas yang setara. Dengan kata lain, tabung gas akan lebih cepat habis dari biasanya atau proses memasak lebih lama 20% jika hanya menggunakan DME tanpa modifikasi kompor.
Meski pemerintah telah berencana untuk mengakali harga DME dengan menggunakan batu bara berkalori rendah agar lebih murah, masyarakat akan tetap mengeluarkan biaya pengeluaran yang lebih banyak akibat borosnya penggunaan DME.
Titik didih atau boiling point DME yang lebih tinggi (-25°C) dibandingkan dengan LPG (-42°C) juga memaksa masyarakat untuk membeli kompor baru. Semakin rendah titik didih suatu zat, semakin tinggi tekanan uapnya pada suhu ruangan.
Oleh karena titik didih DME lebih tinggi dibandingkan LPG, DME memiliki tekanan uap lebih rendah dibanding LPG pada suhu yang sama. Sementara kompor LPG yang ada saat ini tidak dapat mengalirkan DME dengan efisiensi yang sama, sehingga perlu modifikasi atau perangkat tambahan. Ini berarti penggunaan DME akan memicu biaya tambahan.
Memperparah perubahan iklim
Proyek gasifikasi batu bara juga bakal menambah emisi gas rumah kaca, sehingga justru berlawanan dengan upaya global melawan perubahan iklim.
Penelitian Joint Research Center European Commission (JRCEC) di tahun 2020 menyebut, proses produksi DME dari batu bara menghasilkan emisi sebesar 153 kg CO2 per setara barel minyak (SBM). Sementara pembakarannya menghasilkan 412 kg CO2 per SBM—lebih tinggi dibanding emisi pembakaran LPG yakni 386 kg CO2 per SBM.
Ini diperparah dengan adanya gas metana (CH4) dari proses gasifikasi dan sintesis untuk menghasilkan DME dari batu bara. Metana merupakan gas rumah kaca yang 28 kali lebih kuat memerangkap panas di atmosfer dibandingkan CO2.
Proyek ini juga berisiko menjauhkan Indonesia dari target penghentian batu bara di tahun 2040 karena meningkatkan ketergantungan Indonesia pada batu bara 25 tahun ke depan. Pasalnya, kebutuhan energi normal (skenario Business as Usual) Indonesia mencapai 47,7 juta ton setara minyak (Mtoe) pada 2050, sehingga permintaan DME untuk menggantikan LPG akan terus naik.
Low Carbon Development Indonesia di tahun 2022 telah menghitung, jika DME mulai menggantikan LPG sebanyak 12% sejak 2025 hingga 2030, maka emisi karbon berisiko meningkat sebesar 1,9 juta ton CO2 pada 2025 dan 2,4 juta ton CO2 pada 2030, dibandingkan dengan emisi dari penggunaan LPG.
Memperbaiki arah investasi Danantara
Alih-alih berinvestasi sembari menambah emisi, Danantara yang akan diproyeksikan menjadi salah satu dari lima SWF (sovereign wealth fund) terbesar di dunia seharusnya memaksimalkan aset dengan mengambil langkah relevan dengan tren investasi global.
Salah satu yang bisa dilakukan Danantara adalah memanfaatkan dana Rp180 triliun pada proyek tenaga surya. Misalnya, membiayai PLTS off-grid di wilayah terpencil yang tidak terjangkau jaringan PLN. Ditambah, biaya teknologi energi terbarukan kini semakin hari semakin terjangkau.
Analisis International Renewable Energy Agency pada 2023 memaparkan, energi surya telah mengalami penurunan harga yang signifikan, dengan rata-rata sekitar US$30-50 per megawatt-jam (MWh).
Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) contohnya, dengan aset yang jauh lebih kecil dibanding Danantara, yakni hanya CA$699,6 miliar atau sekitar 58% dari Danantara, justru memiliki portofolio besar dalam transisi energi, termasuk investasi pada tenaga surya, angin, dan teknologi hijau. CPPIB menginvestasikan CA$741 juta atau setara Rp8,4 triliun pada enam proyek tenaga angin dan surya milik NextEra Energy Partners, LP yang beroperasi di Kanada—angka investasi yang besarnya hanya 4,67 % dari rencana investasi gasifikasi batu bara Indonesia.
Sementara Caisse de dépôt et placement du Québec (CPDQ), SWF Kanada lainnya, mengalokasikan investasi sebesar US$1 miliar atau setara 16 triliun rupiah pada Invenergy Renewables LLC, untuk proyek angin dan surya terbesar di Amerika Utara. Bahkan, CPDQ berani mengambil langkah untuk menghentikan investasi minyak di tahun 2021 dan beralih ke energi bersih.
Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar meninjau ulang arah investasi Danantara yang tidak memprioritaskan proyek infrastruktur energi terbarukan. Upaya yang hanya berfokus pada kepentingan jangka pendek akan merugikan Indonesia jauh lebih dalam, serta mengingkari hak masyarakat untuk hidup sejahtera dalam lingkungan yang bersih dan sehat.
Editor: Robby Irfany Maqoma