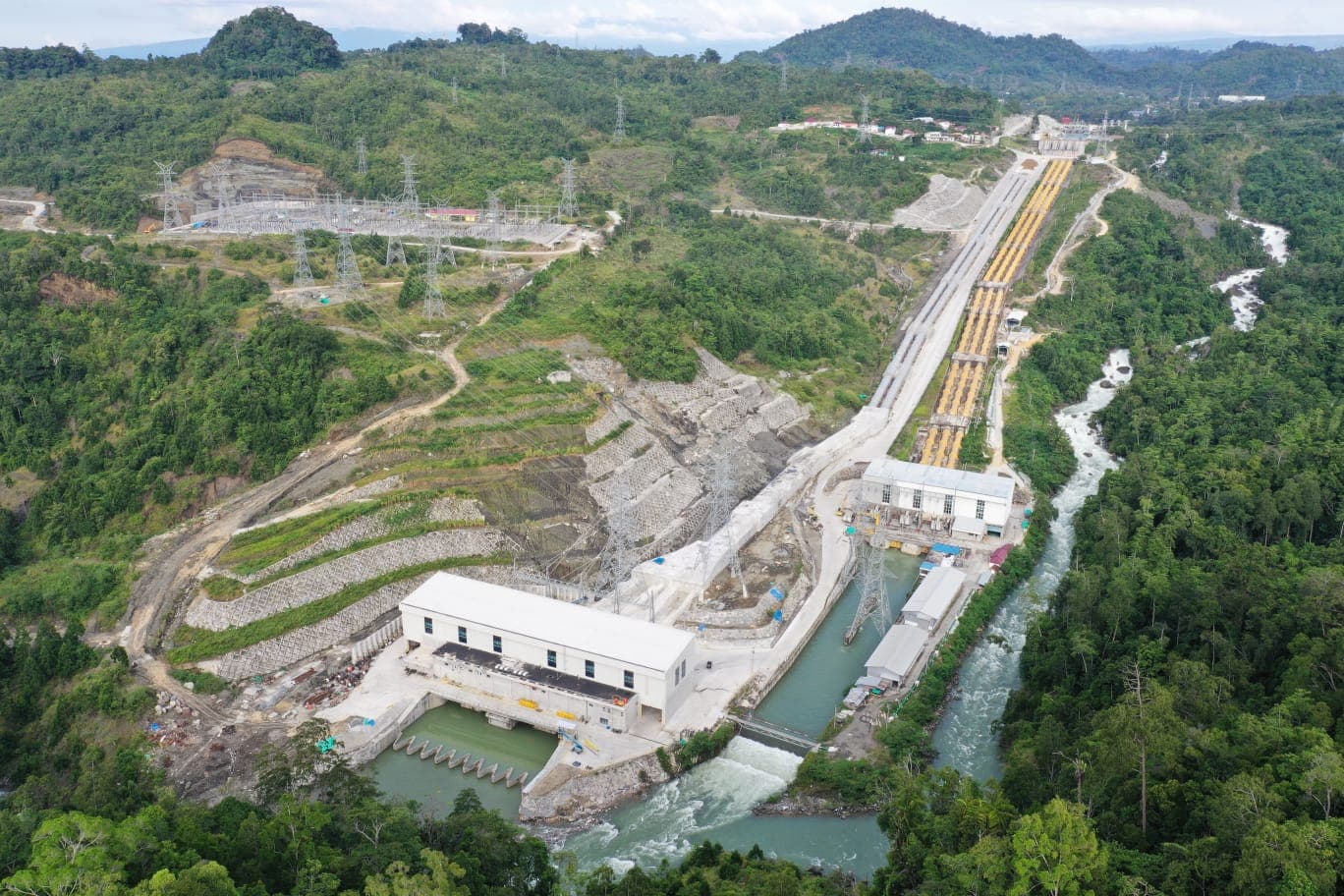Evaluasi Hibah PLTS Atap: Tak Menyentuh Masyarakat Desa, Belum Memberdayakan yang Rentan
Sita Mellia • Penulis
31 Juli 2025
124
• 6 Menit membaca

Indonesia memiliki kekayaan energi surya yang berlimpah, dengan potensi sebesar 7.714,6 gigawatt (GW). Sebagian di antaranya—yakni sekitar 32,2 GW, dapat dipanen dari pembangkit listrik tenaga surya di atap bangunan (PLTS atap).
Untuk pemerataan akses listrik sekaligus meningkatkan penggunaan PLTS, pemerintah beberapa kali menggelontorkan dana hibah PLTS atap. Salah satunya adalah hibah Sustainable Energy Fund (SEF), kemitraan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama United Nations Development Programme (UNDP). Wujud dari insentif ini berupa voucher untuk meringankan biaya pemasangan PLTS atap, dengan total hibah senilai Rp. 23,62 miliar.
Sayangnya, keberadaan dana hibah PLTS atap tak serta merta menyelesaikan elektrifikasi atau memeratakan akses listrik. Per Juli 2025, sebanyak 1,28 juta rumah tangga masih belum teraliri listrik.
Dengan dana yang tak sedikit, mengapa hibah PLTS atap belum menyentuh akar masalah? Apakah pendekatannya masih keliru karena hanya fokus pada target bauran energi bersih, bukan keadilan?
Tak tepat sasaran
Hibah PLTS atap selama ini hanya bertujuan untuk memenuhi target bauran energi bersih semata. Program ini belum menjawab kebutuhan akses listrik warga di daerah terpencil maupun mengurangi beban rumah tangga kurang mampu.
Hibah SEF yang berkapasitas 5 megawatt peak (MWp) ini hanya ditargetkan untuk sekitar 1300 pelanggan PT PLN (Persero) yang telah memasang PLTS atap yang terjaring PLN tetapi belum beroperasi per 1 Desember 2021. Mereka mulai dari level rumah tangga, sosial (sekolah/bangunan pendidikan, rumah sakit, rumah ibadah), bisnis, dan industri terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Artinya, hibah hanya berlaku bagi warga atau institusi yang telah memasang PLTS atap on-grid atau tersambung ke jaringan PLN.
Sayangnya, realisasi jauh panggang dari api. Dari target 1.296 pelanggan, realisasi penerima hibah hanya mencapai 383 orang pada Desember 2022—atau sekitar 30%.
Angka yang sedikit ini mungkin masuk akal. Sebab, hibah hanya berlaku bagi rumah tangga yang sudah memasang panel surya yang terhubung PLN. Sementara warga pun masih kesulitan memasang panel surya karena biaya instalasinya masih mahal. Survei IESR di 7 provinsi dalam kurun 2019 – 2021 menunjukkan bahwa rendahnya biaya pemasangan panel surya menjadi salah satu alasan penting dan penentu bagi pelanggan residensial untuk menggunakan PLTS atap.
Tak heran, output dari hibah ini hanya sebatas mengurangi beban tagihan listrik pada bangunan universitas, sekolah, UMKM, dan rumah sakit di perkotaan. Singkatnya, hibah ini hanya dijangkau masyarakat perkotaan yang terjaring PLN. Warga di pedesaan apalagi kelompok rentan di daerah terpencil yang belum tersaluri listrik sulit mengakses hibah ini.
Pada tahun yang sama dengan hibah ini disosialisasikan, warga semakin kehilangan minatnya memasang PLTS atap. Sebab, pemerintah menghapus skema jual beli listrik melalui Permen ESDM 2/2024. Akibatnya, rumah tangga yang telah memasang PLTS atap tidak bisa menjual kelebihan listriknya ke PLN.
ESDM beralasan bahwa kebijakan ekspor-impor listrik rumah tangga membebani sistem kelistrikan nasional dan menyebabkan ketidakseimbangan pasokan, terutama di wilayah dengan kelebihan kapasitas seperti Jawa-Bali. Dalih ini terhitung klasik dan sebetulnya bisa diatasi dengan modernisasi jaringan.
Hibah PLTS atap belum transformatif
Sebuah pendanaan iklim bisa menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan apabila sudah transformatif. Maksudnya, pendanaan ini menghasilkan perubahan positif dan berkelanjutan di tingkat pasar dan sistem yang lebih luas, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan iklim dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang lebih luas.
Pada 2025, Climate Policy Initiative (CPI) telah menyusun sepuluh dimensi kunci untuk mengukur kualitas—seberapa transformasional—sebuah pendanaan iklim. Sepuluh dimensi itu ialah accessibility, affordability, co-benefits, commercial viability, coordination and partnerships, enabling environment, equity and justice, mobilization, ownership, dan programmatic approaches.
10 dimensi untuk mengukur kualitas pendanaan iklim publik versi Climate Policy Initiative (2025)
Jika menilai hibah PLTS atap SEF dengan kacamata kerangka CPI, hampir seluruh indikator kualitas tersebut belum terpenuhi. Terutama ketika ingin melibatkan kelompok rentan dalam transisi energi, kita bisa melihat betapa lemahnya hibah SEF dalam aspek accessibility, affordability, equity and justice, dan co-benefits.
Dari sisi accessibility dan affordability, hibah SEF memiliki persyaratan rumit dan hanya untuk kelompok tertentu (pelanggan PLN) sehingga tidak inklusif. Program ini juga tidak menyentuh co-benefits seperti pengurangan beban tagihan listrik bagi rumah tangga miskin dan peningkatan akses energi bersih di daerah marginal. Penerima manfaatnya terbatas pada rumah tangga kelas menengah atas yang telah mampu memasang PLTS atap.
Alih-alih menjadi katalis perubahan, hibah SEF hanya memperkuat status quo: sistem listrik yang tersentralisasi dan padat kepentingan.
Sejahtera dari PLTS atap
Pemerintah bisa melakukan hal lebih jauh dari sekadar memberi insentif, yakni menebalkan kantong warga kelas bawah dari penjualan listrik PLTS atap. Rumah tangga miskin bisa memanfaatkan PLTS atap sebagai sumber penghasilan tambahan atau penghematan biaya listrik jangka panjang.
Pemerintah Cina, misalnya, pernah membuat program pengentasan kemiskinan lewat energi surya atau Solar Energy Poverty Alleviation Program (SEPAP). Program ini juga disebut Photovoltaic Poverty Alleviation Projects (PPAPs). Dananya berasal dari percampuran antara subsidi pemerintah dan dana CSR perusahaan swasta—disebut juga sebagai blended finance.
Inisiatif ini mulanya muncul dari pemerintah Cina pada 2014 karena mencoloknya ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan, serta tingginya angka kemiskinan di wilayah terpencil yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik konvensional. Targetnya, program ini menambah kapasitas energi surya sebesar 10 GW pada 2020, dan membantu lebih dari 2 juta orang masyarakat miskin di daerah terpencil—sekitar 35 ribu desa miskin yang berlokasi di 471 kabupaten di 16 provinsi.
Hasilnya signifikan. Studi Zhang et al (2020) yang meneliti 211 kabupaten dalam kurun 2013 hingga 2016 menunjukkan, program ini berhasil meningkatkan pendapatan per kapita kabupaten rata-rata sebesar 7-8%. Sementara penelitian Liu et al. (2021) yang meneliti 735 keluarga miskin sebelum dan sesudah program dimulai menemukan, program ini membantu meningkatkan modal sosial-ekonomi keluarga miskin di pedesaan sebesar 31%.
Peningkatan terjadi karena warga dapat menjual kelebihan listriknya ke State Grid Corporation of China (SGCC)—perusahaan listrik Cina. Hasilnya, program ini meningkatkan pendapatan tahunan per rumah tangga sebesar 3.000 RMB atau US$ 400 - 500 selama 20 tahun lebih.
Apa yang telah dilakukan Cina bukan sekadar transisi energi yang berkeadilan, tetapi juga memberdayakan warga agar terus berpenghasilan.
Momentum menggeser paradigma
Di tengah krisis pendanaan iklim, pemerintah seharusnya memaksimalkan hibah PLTS atap untuk memeratakan akses listrik sekaligus memberdayakan warga, bukan sekadar memenuhi target bauran energi terbarukan.
Kementerian ESDM dapat mengadopsi kerangka berpikir CPI ataupun mencontoh langkah pemerintah Cina. Harapannya, program hibah PLTS atap ataupun pengembangan energi terbarukan lainnya bisa mencapai beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) seperti energi bersih dan terjangkau, sembari menekankan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan.
Sudah saatnya pula ada pergeseran desain pendanaan iklim yang mendorong perubahan transformatif: menyasar kelompok miskin, menggunakan skema blended finance (kolaborasi pemerintah dan swasta), serta membangun insentif jangka panjang yang memungkinkan warga turut serta dalam transisi energi.