Setengah Hati Aksi Iklim SNDC: Kontradiksi di balik Motif Ekonomi
Sita Mellia • Penulis
12 November 2025
45
• 6 Menit membaca
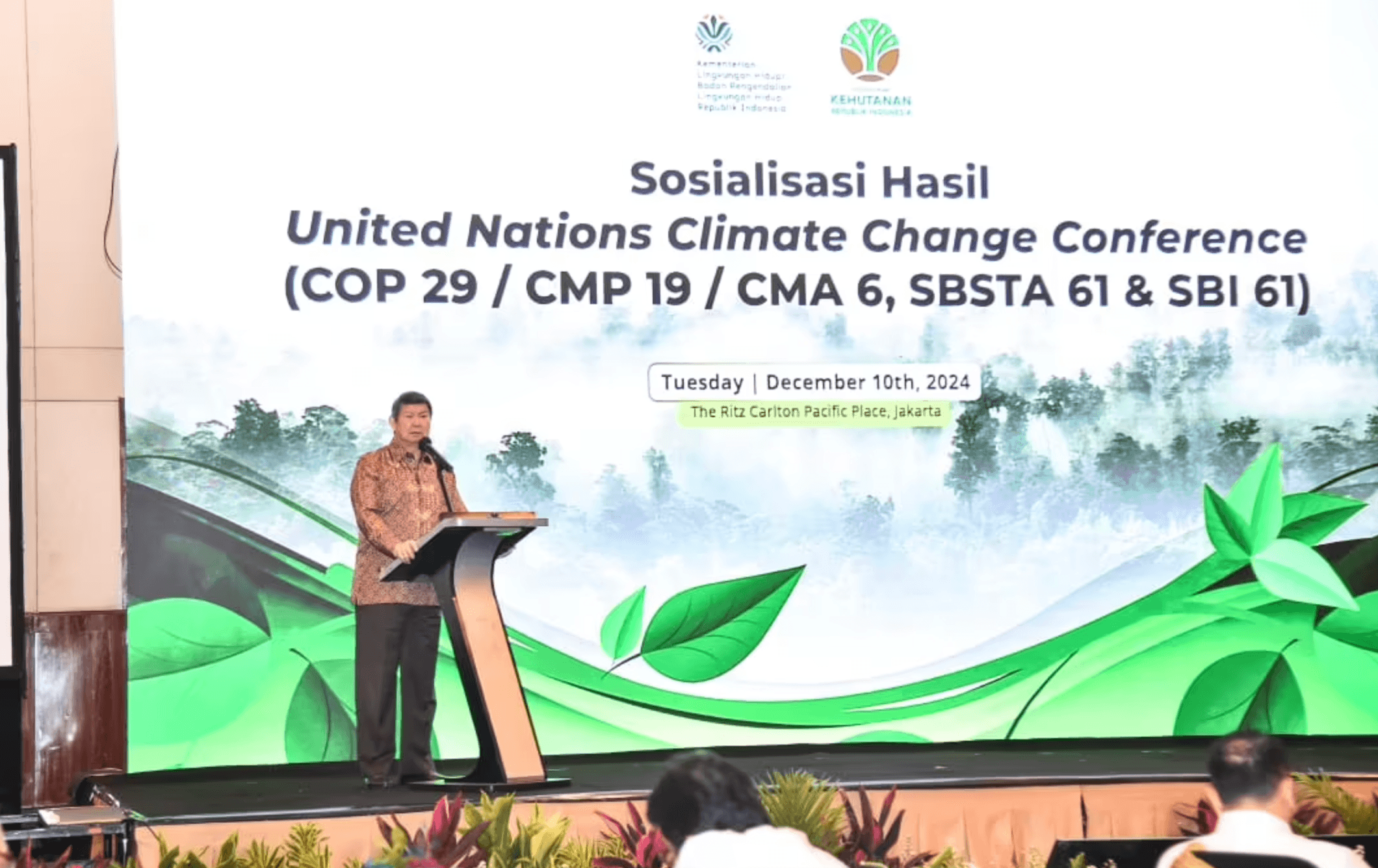
Sepuluh tahun pasca-Perjanjian Paris, target iklim Indonesia masih belum selaras dengan upaya global menahan laju pemanasan suhu Bumi 1.5°C. Ini termuat dalam Second Nationally Determined Contributions (SNDC) yang diserahkan pemerintah ke Perserikatan Bangsa Bangsa pada akhir Oktober lalu.
Bukan hanya itu, seberapa ambisius upaya mengurangi emisi akan bergantung pada cepat atau lambatnya laju pertumbuhan ekonomi. Kata ‘ekonomi’ sendiri muncul sebanyak 50 kali di dalam komitmen yang seharusnya menyelesaikan masalah iklim yang lebih fundamental.
Target ini sepintas masuk akal, mengingat pertumbuhan ekonomi dunia sejak era praindustri (1850-an) ditopang oleh konsumsi energi fosil seperti batu bara serta minyak dan gas fosil—penyebab utama perubahan iklim. Namun sebenarnya, geliat ekonomi berbasis energi fosil justru merugikan perekonomian secara keseluruhan karena kualitas hidup yang menurun, beban kesehatan yang meningkat, dan sebagainya.
SNDC Indonesia juga memuat aksi iklim sektor energi yang kontradiktif dari tujuannya, yakni mengurangi emisi sambil menumbuhkan ekonomi.
Ketidakjelasan arah SNDC ini patut dipertanyakan, sebab pemerintah terlihat setengah hati menyelesaikan krisis iklim.
Risiko inflasi dari aksi iklim
Target iklim dalam SNDC terang-terangan dibuat dengan mengikuti dua skenario pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan ekonomi melambat (LCCP_L), maka emisi gas rumah kaca maksimal yang dihasilkan pada 2030 ialah 1,345 gigaton CO2e, dengan target penurunan emisi 1,257 gigaton CO2e pada 2035.
Sementara skenario kedua, apabila perekonomian tumbuh lebih cepat (LCCP_H), emisi gas rumah kaca maksimal yang dihasilkan pada 2030 ialah 1,491 gigaton CO2e, dan pada 2035, emisi ditargetkan turun menjadi 1,488 gigaton CO2e.
Target yang mengikuti dua jenis pertumbuhan ekonomi ini tak lain karena SNDC merujuk pada Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% pada 2029.
Masalahnya, sulit menganggap aksi iklim pemerintah—khususnya di sektor energi—sebagai upaya mengurangi emisi. Apalagi berbagai proyek strategis juga masih digenjot melalui eksploitasi tanpa pengendalian.
Guna mengurangi impor minyak dan emisi kendaraan misalnya, SNDC mencantumkan upaya menggenjot pencampuran biodiesel. Campuran biodiesel yang di tahun ini mencapai 40% (B40) rencananya akan ditambah sebagai langkah transisi energi.
Aksi menggenjot biodiesel bertolak belakang dengan tujuan mengurangi emisi. Misalnya, emisi dari proses produksi biodiesel berbahan baku minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) enam kali lipat lebih tinggi dibanding emisi dari energi fosil. Jika strategi ini dipertahankan, upaya mengurangi emisi sektor energi justru memicu kenaikan emisi di sektor lainnya—seperti hutan dan lahan.
Upaya tersebut juga belum tentu membuahkan manfaat ekonomi—justru sebaliknya. Penelitian di tahun 2022 menemukan, dalam skenario implementasi biodiesel 30% (B30) saja akan menimbulkan dampak ekonomi. Di antaranya adalah kenaikan harga komoditas pertanian seperti gula, sayuran, dan kedelai. Kenaikan harga komoditas ini berisiko memengaruhi inflasi nasional.
Selain kenaikan harga pangan, kelangkaan minyak goreng juga akan membayangi masyarakat jika Presiden Prabowo berambisi mewujudkan B100. Alhasil risiko kenaikan pencampuran biodiesel berisiko mengulangi krisis minyak goreng 2022 yang diduga terjadi karena persoalan serupa.
Transisi energi yang dipilih dalam SNDC ini pada akhirnya menghambat konsumsi rumah tangga yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Terhambatnya konsumsi berefek domino ke masyarakat kelas menengah yang berisiko kesulitan naik kelas.
Padahal, salah satu syarat untuk menjadi negara kaya ialah memiliki kelas menengah yang kuat, sebab mereka menjadi penggerak ekonomi. Aktivitas ekonomi mereka lah yang akan membantu mengungkit perekonomian warga kelas bawah.
Melemahkan ekonomi desa
Bukan hanya mengimpit kelas menengah, aksi iklim lewat ekspansi bahan bakar nabati juga melemahkan perekonomian warga kelas bawah di daerah. Sebab, ekspansi tersebut memicu pembukaan lahan, sehingga rawan memperparah perampasan lahan masyarakat.
Apalagi banyak masyarakat adat yang belum memiliki kekuatan hukum atas tanahnya. Studi menunjukkan, pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi jika masyarakat adat—yang jumlahnya mencapai 70 juta jiwa—tak memiliki kekuatan hukum atas tanah mereka.
Selain masyarakat adat, pemerintah seakan luput memikirkan kesejahteraan petani lokal. Dana subsidi biodiesel selama ini hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar. Karena kebijakan perkebunan sawit Indonesia berat sebelah ke korporasi, biofuel justru memperpanjang kerugian petani. Alih-alih membawa kesejahteraan, kebijakan biodiesel Indonesia berpotensi memperparah ketimpangan.
Dalam kebijakan B50 yang akan dimulai pada 2026, Indonesia perlu memasok minyak sawit sekitar 19 hingga 20 juta kiloliter (KL) per tahun. Untuk memenuhi target ini, perlu lahan konsesi tambahan sekitar 2,3 juta hektare—setara empat kali luas Pulau Bali. Sejauh ini, SNDC maupun dokumen kebijakan lainnya tak menyertakan data yang transparan soal lahan mana yang akan menjadi lokasi ekspansi kebun sawit untuk memenuhi kebutuhan biodiesel.
Silang tujuan emisi pembangkit
Salah satu aksi mitigasi iklim adalah mempercepat produksi kendaraan listrik. Namun, ini sulit tercapai jika listrik Indonesia mayoritas masih berasal dari batu bara. Ditambah, proses memproduksi baterai di hulu—smelter nikel—yang masih menggunakan energi kotor.
Mayoritas industri baterai kendaraan listrik—nikel—masih menggunakan energi kotor yang menggerus kualitas hidup warga. Studi pada 2024 menyebut, beban kesehatan yang ditanggung warga akibat PLTU batu bara captive akan menguras kantong mereka hingga US$ 20 miliar. Jika tidak segera dikendalikan, polusi udara dari smelter yang menggunakan PLTU captive diprediksi akan menyebabkan 5.000 kematian dan beban ekonomi US$ 3,42 miliar pada 2030.
Warga pun akan menanggung beban tersebut dalam enam tahun ke depan. Ini ditandai dengan adanya tambahan kapasitas lebih dari 20 gigawatt (GW) PLTU captive baru, atau setara 74,6% PLTU batu bara baru nasional hingga 2031 dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).
Tak berhenti di situ, emisi akan terus bertambah akibat naiknya kapasitas pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang melepas gas metana. Imbasnya, pemerintah harus menanggung beban klaim BPJS kesehatan pada 2040 sebanyak Rp1,5 ribu triliun dengan skenario pembangkit gas fosil 2,68 GW.
Kerugian ini tak hanya berdampak pada APBN, tetapi juga kelas pekerjanya. Pembangkit gas berpotensi menurunkan serapan tenaga kerja hingga 6,7 juta orang, angka ini mempertimbangkan gangguan yang terjadi pada pendapatan warga di dua sektor terdampak seperti kelautan dan perikanan.
Transisi berkeadilan: emisi berkurang, kesejahteraan bertambah
Jika pemerintah sungguh-sungguh ingin menumbuhkan perekonomian sambil mengurangi emisi, maka opsi yang seharusnya dipilih ialah menyentuh terlebih dulu kelompok rentannya.
Ini bisa dimulai dari mempermudah akses energi bersih dengan memberikan subsidi PLTS atap untuk rumah tangga kelas menengah-bawah seperti yang dilakukan Cina. Pemerintah Cina yang kala itu ingin mengentaskan kemiskinan di wilayah terpencil, berhasil menumbuhkan ekonomi 7-8% per kabupaten akibat menurunnya beban tagihan listrik serta bertambahnya penghasilan warga dari penjualan listriknya. Selain memutus rantai kemiskinan warga, ini membantu mereka memiliki akses mudah terhadap energi matahari yang tak pernah habis.
Pilihan lainnya ialah membangun energi terbarukan berbasis komunitas. Masyarakat bisa menggunakan energi terbarukan untuk menciptakan ketahanan pangan mereka di tengah cuaca tak menentu akibat krisis iklim.
Center of Economics and Law Studies (CELIOS) telah menghitung, energi terbarukan berbasis partisipasi komunitas berpotensi menurunkan angka kemiskinan hingga lebih dari 16 juta orang pada 25 tahun ke depan. Ini juga menyumbang ke PDB sebesar Rp10,5 ribu triliun. Angka ini cukup signifikan mendorong perekonomian nasional.
Jika Indonesia mau bergeser ke ekonomi restoratif, maka ekologi dan ekonomi bisa tumbuh bersamaan—tak harus berlawanan.





