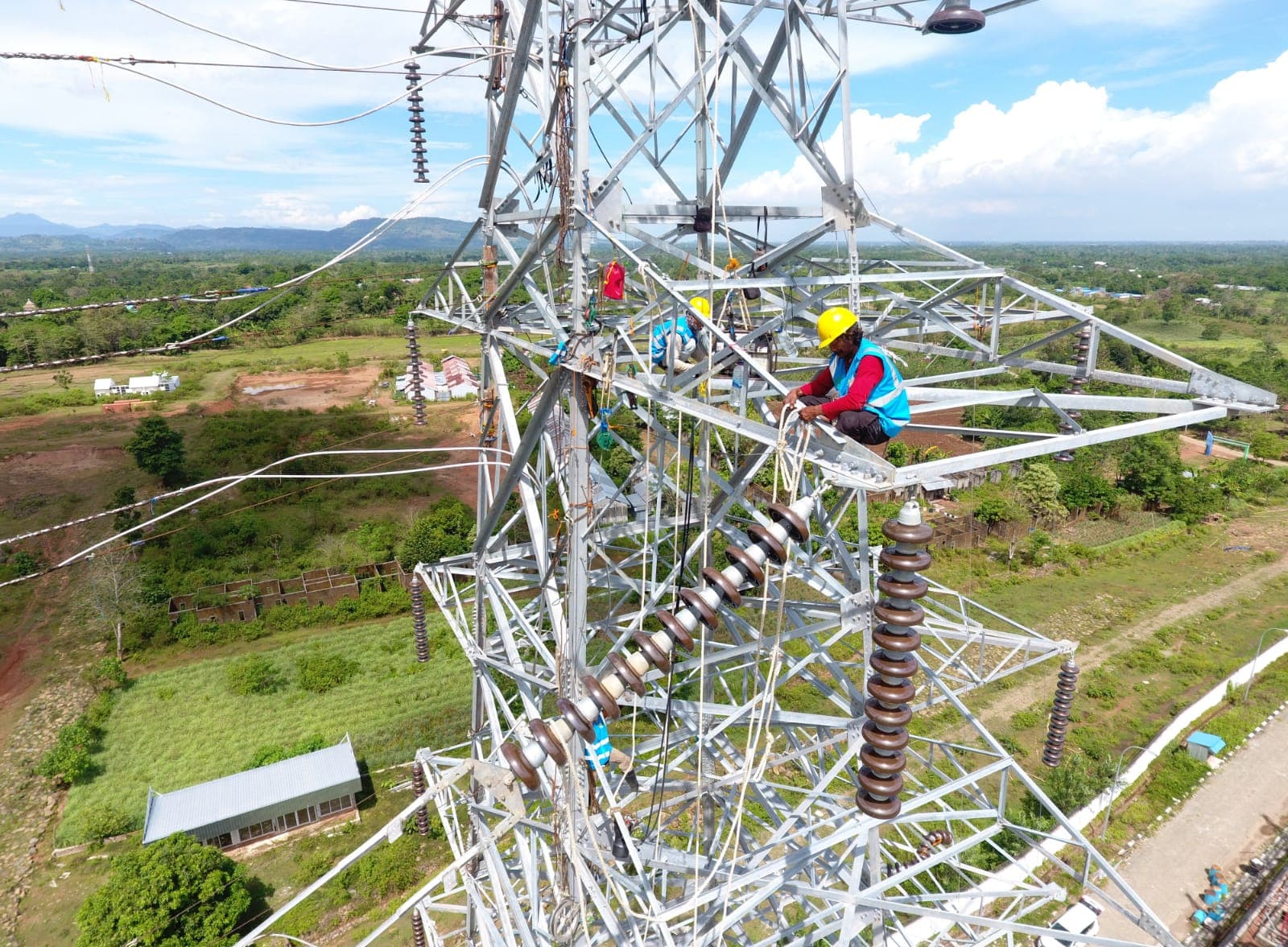Memastikan Transisi Energi Berkeadilan bersama Cina
Sita Mellia • Penulis
30 September 2025
8
• 7 Menit membaca

Cina tengah menjadi investor menjanjikan untuk energi terbarukan, layaknya oase di tengah keringnya pendanaan. Selama dua tahun terakhir, kesepakatan hijau Indonesia-Cina telah menyentuh US$ 22,6 miliar. Ke depannya, hingga 2030, tren investasi Cina untuk sektor energi di Indonesia diprediksi mencapai US$2,1 hingga US$9,3 miliar per tahun.
Indonesia harus memanfaatkan momentum Presiden Cina, Xi Jin Ping, yang ingin menjadi pemimpin investasi energi bersih dan lapangan pekerjaan hijau. Namun, kita juga harus tegas terhadap investasi yang masuk untuk memastikan kucuran modalnya tak menambah masalah baru.
Meski selama ini investasinya di sektor energi menciptakan lapangan kerja, jejak investasi Cina juga melahirkan ketimpangan. Lapangan pekerjaan tumbuh masif di wilayah industri pengolahan nikel menjadi baterai kendaraan listrik seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Di sisi lain, taraf hidup warga terdampak di daerah ekstraktif terus turun akibat pencemaran dan pelanggaran hak asasi pekerja oleh perusahaan Cina.
Pemerintah sudah harus menarik batas tegas antara hitam dan putih di atas kertas perjanjian sebelum menggenjot proyek transisi energi lainya bersama Cina. Jika tidak, proyek energi terbarukan di Indonesia hanya mengulang siklus greenwashing—terlihat hijau di luar, tetapi sebenarnya menambah masalah sosial-ekologis baru.
Rapor merah Indonesia-Cina
Pihak Danantara mengklaim bahwa tiga hingga empat perusahaan Cina tengah menjajaki investasi untuk memproduksi kendaraan listrik. Ini seiring dengan dihentikannya insentif atau keringanan pajak untuk pembelian mobil listrik impor langsung jadi mulai 2026 sehingga produsen harus membangun pabrik di Indonesia.
Masalahnya, beberapa merek mobil listrik buatan Cina yang selama ini menghijaukan perkotaan masih diwarnai pelanggaran HAM di hulu. Salah satu penyebabnya ialah perusahaan Cina yang mendominasi industri hilirisasi nikel nasional memiliki tata kelola mineral untuk transisi energi bersifat top-down—terpusat pada negara dan korporasi. Akhirnya, warga lokal terpinggirkan dari proses pengambilan kebijakan.
Sebut saja BYD, merek mobil listrik terlaris asal Cina ini diberi skor performa HAM 11 dari 90 oleh Amnesty International pada 2024. BYD tercatat pernah dibekukan pabriknya oleh otoritas Brasil pada 24 Desember karena kasus perbudakan modern. Cerita ini tak boleh terulang di Indonesia, mengingat BYD tengah membangun pabrik di Subang, Jawa Barat, yang akan merekrut sebanyak 18 ribu tenaga kerja.
Pemerintah Indonesia yang telah bersusah payah memudahkan investasi Cina untuk menggenjot hilirisasi nikel juga harus serius mengevaluasi perlakuan investor kepada para pekerja. Sebab, alih-alih sejahtera, pekerja smelter nikel menjadi kelompok rentan paling terdampak. Sembada Bersama Indonesia mencatat, sejak 2019 hingga 2025, ada 104 kecelakaan kerja di seluruh smelter nikel Indonesia. Karena kecelakaan tersebut, sebanyak 107 orang harus meregang nyawa serta 155 orang lainnya luka-luka.
Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) misalnya, investasi ‘hijau’ terbesar Cina di Tanah Air ini menjadi potret buram transisi energi, baik bagi pekerja WNI maupun pekerja asal Cina sendiri. Sejak 2023 hingga Mei 2025, terhitung ada 43 pekerja yang meninggal akibat kecelakaan kerja.
Berdasarkan survei, ada dua alasan utama mengapa angka kecelakaan kerja di IMIP tinggi. Pertama, pekerja IMIP rata-rata harus bekerja 56 jam dalam seminggu atau 225 jam dalam sebulan, 40% lebih lama dari pekerja pada umumnya. Kelelahan ini menambah risiko kecelakaan kerja. Kedua, minimnya pengawasan sistem K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) yang diakibatkan oleh pembiaran pengawas. Dengan kerentanan ini pun mereka masih diberi upah yang jauh dari kata layak.
Cara IMIP memperlakukan tenaga kerjanya sangat kontroversial. Sejak awal proses perekrutan, informasi nama perusahaan dirahasiakan kepada calon pekerja. Pekerja juga seringkali dipindahkan atau dimutasi tanpa persetujuan pekerja dan tanpa dokumen ketenagakerjaan yang jelas.
Tak hanya dari kelompok pekerja, nelayan juga menjadi korban dari transisi energi yang tak berkeadilan. Analisis Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) bersama Center of Economic and Law Studies (CELIOS) pada 2024 menunjukkan, meski pembangunan smelter nikel tahap awal menyerap banyak tenaga kerja, terdapat penurunan PDB di tahun ke sembilan akibat deforestasi, degradasi lahan, tercemarnya air, dan rusaknya biodiversitas. Hal ini lantaran sebagian besar warganya yang bermata pencaharian sebagai nelayan kehilangan sumber pendapatan.
Indonesia juga harus memastikan pabrik yang dibangun Cina untuk memproduksi material infrastruktur energi terbarukan memiliki rantai pasok yang ramah lingkungan.
Akhir 2024 lalu, Hongshi Holding Group berencana menginvestasikan US$5 miliar untuk membangun pabrik di Jawa Barat yang akan memproduksi silikon, polisilikon (bahan baku panel surya), serta baterai kendaraan listrik. Investasi ini sayangnya disertai dengan rencana pembangunan PLTU batu bara (captive) berkapasitas 2 GW. Produk-produk yang dihasilkan pabrik ini tak serta merta bisa diklaim pemerintah ramah lingkungan, sebab penambahan PLTU captive dapat memperparah polusi di Jawa Barat yang memiliki kualitas udara buruk.
Ada pula tragedi Rempang Eco-City. Demi membangun pabrik panel surya dan perumahan, proyek ini menggusur paksa warga sekitar yang telah mendiami pulau sejak 1883. Proyek dengan investasi Rp 381 triliun yang ditargetkan rampung pada 2080 ini tak boleh digenjot lagi sebab sudah banyak menelan korban.
Selain Rempang, proyek strategis nasional lain yang perlu diawasi ialah proyek PLTA Kayan terintegrasi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tengah menawarkan proyek strategis nasional PLTA Kayan Cascade ke Cina. Proyek ini mengancam ruang hidup warga sekitar. Masyarakat Suku Dayak Kenyah, yang menumpu hidupnya pada Sungai Kayan, harus berpindah karena tempat tinggalnya terancam tenggelam akibat PLTA Kayan. Padahal, mereka sendiri sama sekali belum menikmati listrik selama lebih dari 50 tahun.
Urgensi ekonomi hijau yang membumi
Dengan melihat rekam jejak di atas, kerja sama hijau antara Indonesia dan Cina sudah harus bertumpu pada paradigma energi terbarukan untuk memerangi kemiskinan dan ketimpangan. Oleh karena itu, pemerintah harus memperketat green safeguarding pada proyek-proyek strategis bersama Cina.
Apalagi sejak 2017, Cina sudah mengeluarkan green BRI (Belt and Road Initiative). Intinya, pemerintah Cina menekankan prinsip ecological civilization (peradaban ekologis), green development concepts (konsep pembangunan hijau), dan efisiensi sumber daya dan keramahan lingkungan. Setahun kemudian, Xi Jin Ping dalam pidatonya pada 2018 mendorong bawahannya untuk menjamin warga hidup berdampingan dengan alam. Ia ingin pemerintahan Cina memiliki kebijakan yang mengutamakan perlindungan dan pemulihan lingkungan. Indonesia bisa mengajak Cina untuk membawa prinsip tersebut ke Indonesia.
Cina sebenarnya menerapkan paradigma transisi berkeadilan di negaranya, melalui subsidi PLTS atap warga di daerah dengan kemiskinan tinggi. Negara yang menyumbang bauran energi surya sebanyak 58% ini berhasil menurunkan angka kemiskinan 7-8% lewat PLTS atap yang membantu mengurangi tagihan listrik warga. Sisa listrik warga desa juga diperbolehkan dijual ke jaringan pusat, hingga mereka mengalami kenaikan modal sosial-ekonomi sebesar 31%.
Membangun ketahanan energi sambil memberdayakan desa seperti di atas tak mustahil selama ada kemauan politik. Sektor ekonomi di Indonesia nyatanya menjadi yang paling banyak disentuh Cina, dengan indeks tertinggi dibanding sektor lainnya yakni 41,2%, menurut Center of Economics and Law Studies (CELIOS) di tahun 2025. Menciptakan ketahanan energi dengan PLTS dapat menambah produktivitas warga desa, sekaligus memeratakan akses ke 1,28 juta rumah yang belum menikmati listrik.
Tarik batas tegas
Indonesia perlu membulatkan kemauan politik untuk membangun energi bersih dan menciptakan lapangan pekerjaan hijau tanpa meninggalkan siapapun. Menjelang agenda konsultasi publik Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP) dari Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) dengan masyarakat sipil, ini momentum yang tepat bagi pemerintah untuk mulai skema kerja sama pendanaan transisi energi bersama Cina yang manfaatnya menyentuh warga akar rumput. Apalagi, Sekretariat JETP Indonesia sendiri sudah berjanji bahwa jantung dari transisi energi adalah kesejahteraan warganya.
Paradigma investasi yang berkeadilan pun harus dipegang Danantara. Badan pengelola investasi yang sudah membawahi PLN—salah satu aktor utama transisi energi. Danantara seharusnya lebih memudahkan mandat untuk mengalihkan investasi energi bersih seperti surya dan angin. Apa lagi, harga surya dan angin sudah semakin murah, yang mana alokasi subsidi dari APBN akan lebih kecil dibanding mensubsidi batu bara.