Mengenal ‘Greenwashing’: Tipu Daya Label Ramah Lingkungan oleh Perusahaan dan Pemerintah
Super Admin • Penulis
22 April 2025
232
• 4 Menit membaca
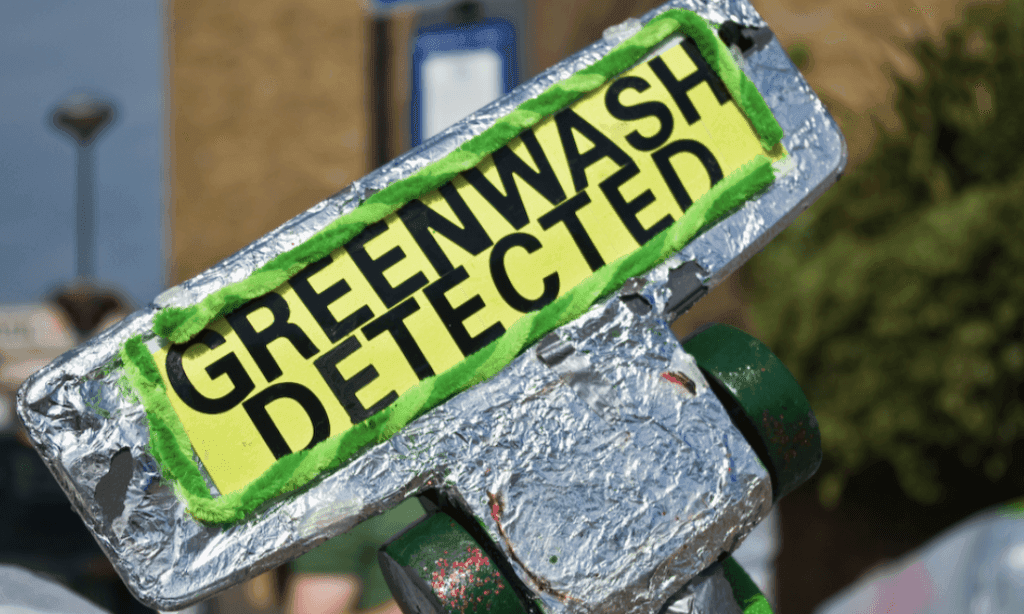
Tren gaya hidup berkelanjutan atau sustainable living semakin meningkat setiap tahun, terlebih setelah pandemi Covid-19 berlangsung. Survei yang dilakukan GlobeScan di sejumlah negara, termasuk Indonesia, menunjukkan 71% orang ingin mengurangi dampak negatif yang mereka berikan pada lingkungan.
Sayangnya, peningkatan minat gaya hidup berkelanjutan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk meraup keuntungan. Tak sedikit dari pihak ini yang mengumbar klaim palsu soal produk ataupun barang ramah lingkungan, padahal sebenarnya tidak (greenwashing).
Istilah “greenwashing” pertama kali muncul dalam esai aktivis lingkungan, Jay Westerveld, yang mengkritik industri perhotelan menggunakan klaim palsu pada 1986. Hotel-hotel tersebut kerap mempromosikan penggunaan kembali handuk sebagai bagian dari strategi ramah lingkungan, padahal niat industri adalah menghemat biaya operasional.
Salah satu jenis greenwashing adalah misinformasi atau menyebarkan informasi yang salah. Lewat penggunaan kata-kata ‘alami’, ‘hijau’, atau ‘berkelanjutan’ yang tidak didasarkan pada bukti saintifik. Hingga kini, klaim palsu dan misinformasi soal label ‘hijau’ makin banyak dilakukan oleh berbagai perusahaan, termasuk di sektor energi.
Ciri-ciri 'greenwashing' di energi
Sektor energi menghasilkan 75,7% dari total emisi gas rumah kaca dunia pada 2021. Tiga sektor yang paling berpengaruh adalah listrik, transportasi, dan manufaktur.
Pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi merupakan penyebab utamanya. Fakta ini menjadi dasar bagi publik—terutama akademisi dan masyarakat sipil—serta Perserikatan Bangsa Bangsa untuk menuntut pemerintah dan perusahaan bahan mengakhiri kegiatan ekstraksi bahan bakar fosil di seluruh dunia.
Namun, tingginya sentimen negatif justru direspons perusahaan-perusahaan bahan bakar fosil melalui penyebaran informasi bahwa mereka turut berupaya memperbaiki lingkungan dan berkontribusi dalam perubahan iklim.
Kenyataannya, perusahaan energi di 55 negara yang ikut berkomitmen pada Perjanjian Paris tidak memiliki niat untuk berusaha menjaga pemanasan global di 1,5°C. Penyelidikan Kongres Amerika Serikat menemukan raksasa minyak seperti Shell, Chevron, dan ExxonMobil hanya berbasa-basi terhadap komitmen tersebut usai menganalisis memo internal mereka. Shell, misalnya, terbukti tidak memiliki rencana untuk beralih ke portofolio emisi bersih dalam 10-20 tahun ke depan.
Raksasa minyak seperti ExxonMobil dan BP pula yang ramai-ramai mendukung teknologi carbon capture and storage (CCS) sebagai klaim upaya ‘berkelanjutan’. Padahal, CCS hanya menjadi cara untuk memperpanjang energi fosil alih-alih menuju energi terbarukan.
Rekam jejak proyek CCS di negara-negara lain pun buruk. Laporan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menunjukkan dari 13 proyek yang diteliti, tujuh berkinerja buruk, dua gagal total, dan satu dihentikan. Salah satu contoh proyek CCS yang berhasil di Norwegia pada 1996 (memasang CCS pada pembangkit gas) lalu adalah cara untuk menghindari pajak karbon yang tinggi, bukan untuk menangani krisis iklim.
Baca juga: Ironi Sawit dalam Solusi Palsu Transisi Energi
Di Indonesia, salah satu perusahaan tambang batu bara besar Adaro ikut mengeluarkan klaim ‘smelter hijau’ untuk rencana pembangunan pabrik peleburan (smelter) aluminium di Kawasan Industri Kalimantan Utara (KIPI). Padahal, pembangunan smelter tersebut akan dibarengi dengan pembangunan PLTU captive (di luar jaringan PLN).
Penggunaan energi terbarukan untuk menyalakan tungku smelter aluminium ini baru dilaksanakan pada 2030. Adaro beralasan masih membutuhkan PLTU batu bara untuk awal operasional.
Tidak hanya perusahaan, pemerintah Indonesia pun ikut-ikutan melakukan greenwashing lewat kebijakan. Contohnya adalah revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang memasukkan biomassa kayu sebagai energi terbarukan. Tujuannya untuk meningkatkan bauran energi terbarukan yang masih rendah dan jauh dari target.
Padahal, riset TrendAsia menunjukkan biomassa kayu berpotensi mengakibatkan deforestasi hingga 1 juta hektare. Lebih jauh, deforestasi tersebut akan menghasilkan gas rumah kaca (GRK) hingga 26,4 juta ton emisi karbon. Untuk memenuhi kebutuhan co-firing 10% di seluruh PLTU Indonesia, kebutuhan lahan dapat mencapai 2,3 juta hektare atau 35 kali luas DKI Jakarta.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dapat dianggap berkontribusi pada upaya greenwashing sektor energi melalui Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). Sistem klasifikasi jenis usaha dalam TKBI kini tidak lagi ditandai lewat kategori “merah, kuning, hijau” melainkan “hijau dan transisi”. Jenis transisi ini dapat mencakup usaha yang tidak berkelanjutan—bahkan terkait pembakaran bahan bakar fosil pun—selama berkomitmen mengurangi emisi dalam kegiatannya.
Baca juga: Membedah Klaim Bahlil Soal Sulitnya Transisi Energi Sesuai Perjanjian Paris
TuK Indonesia menilai perubahan klasifikasi ini sebuah kemunduran bagi usaha mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab. Sebab, kategori “transisi” dapat mengaburkan risiko dan tanggung jawab pemilik usaha.
TKBI pun memasukkan PLTU captive yang notabene masih menggunakan batu bara ke dalam kategori ‘transisi’. Artinya, PLTU captive masih dianggap sebagai sektor yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Meskipun, pembangkit listrik ini turut menghasilkan emisi dan menyebabkan pencemaran, terutama di daerah pengolahan bahan tambang.
Menjaga makna “hijau” sebenarnya
Hari Bumi semestinya menjadi momen penting untuk kembali mengingatkan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan.
Upaya mengenali greenwashing dapat menjadi pemantik kesadaran untuk kembali memilah dan memilih apa yang kita konsumsi, serta mendorong pemerintah dan perusahaan untuk benar-benar merealisasikan komitmennya menyelamatkan Bumi.
Editor: Robby Irfany Maqoma





