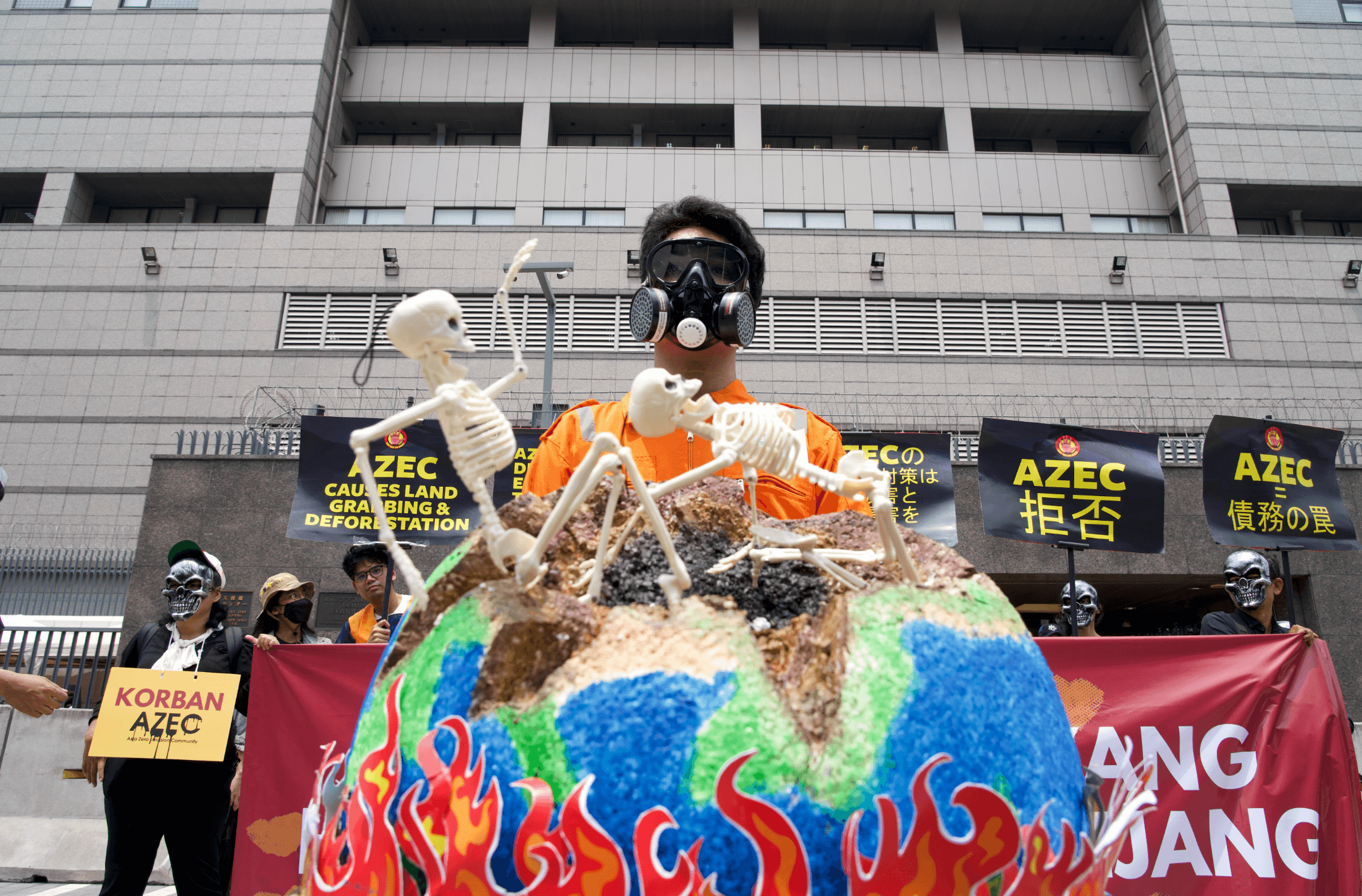Membangun listrik bersih yang tangguh pasca-Banjir Sumatra
Sita Mellia • Penulis
12 Desember 2025
71
• 5 Menit membaca

Pemerintah tengah menargetkan 100 hari pemulihan pascabencana banjir yang melanda 52 kabupaten di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Rencana ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk segera memasukkan pemulihan infrastruktur listrik yang lebih tangguh.
Sistem yang tangguh menjadi prioritas mengingat saat ini Indonesia berada pada posisi harus menjalani dua hal: melakukan dekarbonisasi untuk memitigasi krisis iklim sambil menciptakan sistem kelistrikan yang tangguh terhadap bencana, sebagai akibat dari krisis iklim.
Rentannya kelistrikan Indonesia
Urgensi membangun sistem kelistrikan yang tangguh terhadap bencana iklim telah lama disorot entitas penting, seperti investor global yang memiliki minat investasi hijau.
Laporan Asia’s Powerhouses at Risk oleh Asia Investor Group on Climate Change dan MSCI Institute memprediksi bahwa perusahaan listrik di Asia, termasuk Indonesia, rata-rata akan menanggung kerugian sekitar US$6,3 miliar setiap tahunnya akibat bencana banjir, badai, panas ekstrem, dan cuaca ekstrem pada 2026. Angka ini diperkirakan naik menjadi US$ 8,4 miliar per tahun pada 2050 jika tidak ada adaptasi iklim yang signifikan. Kerugian ini terjadi karena kerusakan aset dan kehilangan pendapatan.
Penyebab utama dari kerugian finansial tersebut ialah ketergantungan perusahaan listrik pada energi fosil, khususnya batu bara dan gas. Dari sebelas perusahaan listrik di Asia, PT PLN (Persero) menempati urutan ketiga sebagai perusahaan listrik paling merugi akibat dominasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG). Ini terjadi karena penggunaan energi fosil berpengaruh kuat terhadap panas ekstrem dan kelangkaan air. Ini terbukti infrastruktur seperti PLTU Nagan Raya yang diduga rusak karena pengaruh dari banjir bandang.
Kerentanan ini juga belum termasuk infrastruktur transmisi dan distribusi yang membentang di atas tanah. Laporan International Energy Agency: Power Systems in Transition: Climate Resilience menegaskan, infrastruktur transmisi dan distribusi di atas tanah jauh lebih rentan terhadap angin kencang, kebakaran hutan, banjir, dan longsor dibandingkan kabel bawah tanah.
Transisi energi terbarukan yang tangguh bencana
Untuk itu, pemerintah perlu mempertimbangkan membangun kabel transmisi dan distribusi di bawah tanah, seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meskipun biaya awalnya tinggi, ini akan dengan signifikan mengurangi potensi kerusakan akibat dampak iklim dan menghemat biaya pemulihan pasca bencana.
Jika membangun seluruh jaringan listrik di bawah tanah dinilai mahal dan sulit, maka langkah paling realistis ialah memilih komponen dan area paling penting –seperti gardu utama dan jalur distribusi ke rumah sakit dan fasilitas umum lainnya– kemudian diprioritaskan untuk dipendam di bawah tanah. Kemudian jika cara ini masih belum realistis, ada dua strategi yang bisa dilakukan untuk melindungi sistem kelistrikan dari banjir, yaitu memindahkan gardu penting ke dataran tinggi atau membangun tanggul untuk melindungi gardu dari banjir.
Amerika Serikat, misalnya, menggelontorkan dana US$ 2 miliar untuk membangun jaringan bawah tanah. Dana ini akan digunakan untuk 32 proyek di 42 negara bagian, termasuk penggalian sebagian saluran transmisi ke dalam tanah, mengangkat gardu di atas area rawan banjir, serta peningkatan kapasitas jalur transmisi yang sudah ada. Jalur transmisi yang dibangun sekitar 1.530 km. Langkah ini guna memperbarui infrastruktur listrik yang sudah tua dan rentan terhadap badai, angin kencang, banjir, atau gangguan cuaca ekstrem lainnya. Ini sehubungan dengan semakin tingginya permintaan listrik untuk data center maupun kendaraan listrik.
Resiliensi energi untuk listrik yang tangguh juga akan bergantung pada kondisi lingkungan. Jika vegetasi tidak terjaga, maka masyarakat rentan mengalami bencana seperti banjir Sumatra. Untuk itu, pemerintah perlu membangun energi terbarukan dengan pendekatan nature-based solutions (NbS). Misalnya, memulihkan vegetasi dan mengurangi membangun energi terbarukan yang berpotensi membabat hutan, seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Belajar dari bencana baru-baru ini, selain alih fungsi lahan sawit, pembangunan PLTA Batang Toru juga diduga turut menyebabkan banjir Sumatra akibat bendungan untuk kebutuhan energi yang tak mampu menahan debit air.
Dalam kurun 100 hari pemulihan pasca bencana, pemerintah juga tak boleh sekadar membetulkan jalan yang rusak. Pemerintah perlu mempertimbangkan membangun jalan dengan pendekatan NbS, seperti membuat terasering agar jalan tak mudah putus lagi. Pasalnya, kerusakan jalan dan putusnya akses akan menaikkan konsumsi energi dan menaikkan tingkat emisi karbon.
Saat infrastruktur pemulihan, masyarakat tetap membutuhkan akses energi bersih dengan harga listrik yang murah. Pemerintah dapat mencontoh apa yang dilakukan UNDP untuk Pakistan pasca dilanda banjir besar. UNDP mendistribusikan paket bantuan yang berisi panel surya, baterai, kipas angin, dan bohlam tingkat rumah tangga kepada 2.200 rumah tangga terdampak. Mayoritas listrik rumah tangga penerima bantuan pun tidak terhubung ke jaringan listrik nasional (off grid), sehingga mengurangi kerentanan jika terjadi pemadaman listrik dari jaringan pusat.
Refleksi pasca banjir Sumatera
Pertama-tama, Indonesia perlu meninjau ulang ambisi biofuel berbasis kelapa sawit atau biodiesel. Banjir Sumatra terjadi salah satunya disebabkan oleh ambisi ekspansi penanaman sawit yang telah melebihi ambang batas.
Sementara untuk membangun sistem yang lebih tangguh, pemerintah bisa mencari pendanaan untuk membangun jaringan bawah tanah sebagai solusi jangka panjang dan memberi paket bantuan panel surya di luar jaringan kepada warga terdampak sebagai solusi sementara. Upaya ini dapat pemerintah usulkan sebagai salah satu proyek dalam Just Energy Transition Partnership (JETP).
Sebagai aksi mitigasi iklim jangka panjang, pemerintah harus mulai mengintegrasikan proyeksi iklim ekstrem di daerah ke dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL). Dokumen ini seharusnya bukan lagi sekadar rencana pemenuhan listrik, tetapi membangun sistem kelistrikan berketahanan iklim. Kemudian, pemerintah dapat memulai pilot project kabel bawah tanah di daerah rawan banjir dan permukiman padat. Ini bisa dimulai dari Sumatera Barat, Aceh, dan NTB yang berulang kali terkena banjir bandang.
Ketiga, pemerintah perlu menghilangkan regulasi yang tumpang tindih. Pendanaan macet apabila tidak ada upaya harmonisasi kebijakan. Regulasi ketahanan energi mulai sekarang perlu saling terintegrasi antarkementerian dan lembaga, mulai dari standar infrastruktur dasar, pengaturan daerah aliran sungai (DAS), hingga desain jaringan listrik.
Kemudian, pemerintah tak perlu gengsi untuk mencari pendanaan pemulihan dari entitas non-parties seperti ADB dan World Bank. Satu tahun pasca banjir bandang melanda Bangladesh, misalnya, World Bank langsung menggelontorkan dana bantuan sebesar US$ 270 juta untuk proyek pemulihan dan rekonstruksi yang berketahanan bencana untuk Bangladesh.