Seberapa Realistis Rencana “Satu Desa Satu PLTS” Pemerintah?
Cintya Faliana • Penulis
28 Oktober 2025
124
• 6 Menit membaca
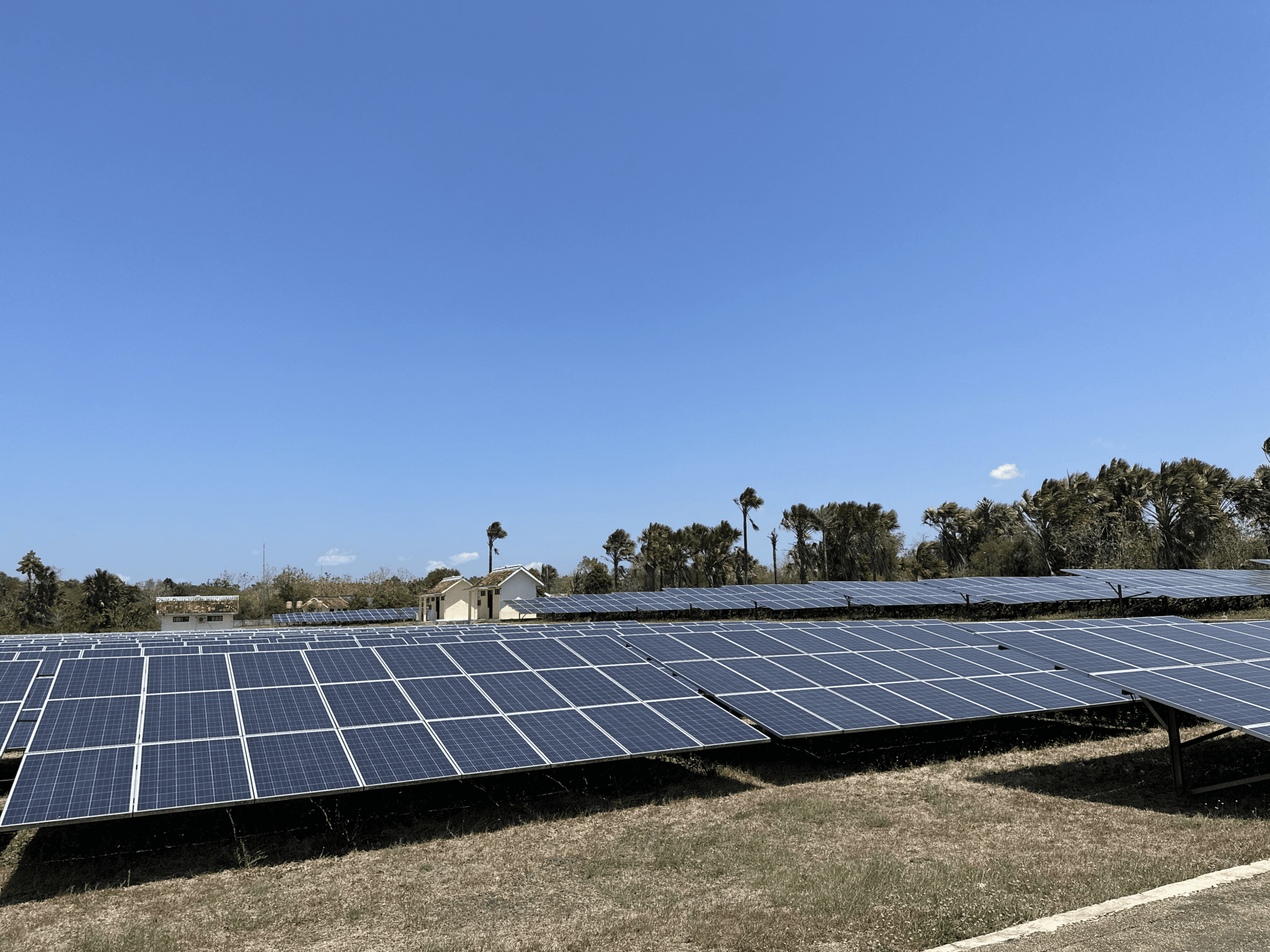
Kredit foto: Maria Putri Adianti & Julia Theresya/IRID
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menerima mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk memulai proyek satu desa satu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Rencananya, setiap PLTS akan berkapasitas 1-1,5 MegaWatt (MW). Secara ambisius, pemerintah ingin mencapai target PLTS 80-100 GigaWatt hingga 2034 mendatang. Nantinya program ini akan direalisasikan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dirancang Presiden Prabowo.
Sepintas, proyek ini dapat menjadi jalan mempercepat transisi energi Indonesia yang selama ini lambat. Namun, ada beberapa hal yang patut diperhatikan agar menghindari mismanagement dan menjadi program mangkrak.
Kapasitas dan kebutuhan lahan berlebih?
Alih-alih langsung mendorong PLTS berkapasitas besar di tingkat desa, pemerintah justru lebih membutuhkan perencanaan PLTS desa yang memadai.
Perencanaan bisa dibuat untuk menjawab pertanyaan: Apakah kapasitas 1-1,5 MW sudah layak bagi desa atau terlalu besar? Desa Muara Enggelam dengan berpenduduk 700 jiwa dengan 174 kepala keluarga (KK) selama ini membutuhkan 42 kilowatt (KW). Sementara penduduk Pulau Medang, Nusa Tenggara Barat, yang terdiri dari 2.574 keluarga bisa menikmati listrik 24 jam dengan PLTS berkapasitas 314 KW.
Faktor lainnya adalah kebutuhan lahan untuk proyek ‘besar’ yang juga akan semakin besar. PLTS Likupang, Sulawesi Utara yang mampu menghasilkan listrik berkapasitas 15 MW membutuhkan lahan seluas 29 hektare. PLTS Oelpuah di Kupang, Nusa Tenggara Timur yang berkapasitas 5 MW berdiri di atas lahan seluas 7,5 hektare.
Maka untuk membangun PLTS berkapasitas 1-1,5 MW, akan dibutuhkan sekitar 1-2 hektare tanah dengan sistem ground-mounted. Dengan luas lahan tersebut, ada risiko benturan fungsi lahan dengan peruntukan lainnya seperti pertanian, budi daya perikanan, ataupun perumahan warga.
Sementara di desa di pulau kecil dengan kepadatan tinggi, seperti di Pulau Bungin; Nusa Tenggara Barat; memasang PLTS dan infrastruktur kontrolnya menjadi tantangan tersendiri karena sulitnya mencari lahan terbuka di tengah padatnya perkampungan.
Sebenarnya ada sejumlah model pengembangan PLTS di tengah benturan kepentingan lahan. Misalnya, PLTS terapung ataupun PLTS agrifoltaik (panel surya di lahan pertanian). Namun tetap saja, tanpa perencanaan dan studi kelayakan yang matang, potensi proyek sulit diterjemahkan menjadi aksi konkret.
Komitmen pendanaan & pemeliharaan
Pertanyaan lain yang muncul ketika Menteri ESDM menyampaikan rencana ini adalah, siapa yang akan membiayai?
Dengan asumsi pembangunan PLTS sekitar US$900 ribu per MW, satu desa setidaknya membutuhkan dana Rp14,9 miliar. Biaya ini jelas sangat besar bagi desa yang hanya menerima dana Rp600 juta-1,6 miliar per tahun. Sementara desa melalui program KDMP hanya mendapatkan plafon pinjaman dari bank sekitar Rp3 miliar selama 6 tahun.
Artinya, dengan asumsi perbankan hanya bisa mendanai PLTS seumur pakainya, yakni rata-rata 25 tahun, maka desa merogoh dana setidaknya Rp12,5 miliar untuk membayar pinjaman pokok. Ini belum dihitung faktor lainnya seperti bunga sebesar 2%, biaya pajak, depresiasi, dan amortisasi, hingga kebutuhan pendanaan unit usaha koperasi lainnya.
Untuk menyiasati keterbatasan ini, sebenarnya ada dua kemungkinan mekanisme yang bisa dipertimbangkan. Pertama, KDMP atau Badan Usaha Milik Desa alias BUMDes (bisa juga kerja sama keduanya) menjadi pemilik dan pengelola sistem bersama. Skemanya bisa berupa sewa infrastruktur ke perusahaan penyedia PLTS. Nantinya BUMDes bisa membayar biaya layanan (service fee) untuk operasional dan pemeliharaan.
Salah satu contoh PLTS yang sudah menggunakan mekanisme ini adalah PLTS Oelpuah, Kupang, Nusa Tenggara Timur. PLTS ini dibangun oleh PT Len Industri (Persero) dan pengelolaannya ditangani oleh PT Surya Energi Indonesia (SEI). Rata-rata, warga hanya perlu membayar Rp60 ribu per bulan untuk akses listrik.
Kedua, kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership/PPP) dengan dukungan hibah berupa Technical Assistance (TA) untuk studi kelayakan. Salah satu contohnya adalah PLTS di Sumba dan Sumba Barat yang mendapatkan pendanaan dari lembaga donor internasional.
Program ini tidak hanya mendukung pembangunan PLTS, tetapi juga mendorong pembentukan dan revitalisasi 20 BUMDes untuk memastikan pengelolaan dan pemeliharaan PLTS bisa berkelanjutan.
Dukungan SDM jadi modal PLTS berkelanjutan
Selain dana, kelayakan teknis dan kapasitas SDM lokal juga krusial. Membangun PLTS di 80 ribu desa akan membutuhkan banyak petugas ahli untuk perawatan.
Akhir 2000-an, Kementerian ESDM sudah pernah punya program hibah PLTS untuk desa-desa terpencil. Pulau Penyalai, Riau menerima hibah PLTS sejak tahun 2009. Sayangnya tak selang lama, sejumlah PLTS rusak dan mangkrak karena kurang pendanaan.
PLTS di Kepulauan Sembilan Sinjai, Sulawesi Selatan yang beroperasi pada 2016 juga mengalami nasib serupa. Warga hanya bisa menikmati listrik murah dan ramah lingkungan selama dua tahun akibat banyaknya modul yang rusak.
Walaupun perwakilan warga sempat menerima pelatihan dari Kementerian ESDM, tapi kerusakan yang terjadi melampaui kemampuan warga untuk memperbaiki. Hanya berumur dua tahun, PLTS tersebut kini ditumbuhi semak belukar. Akhirnya warga kembali memakai generator bertenaga diesel seperti sebelumnya.
Belajar dari pengalaman di Kepulauan Sembilan Sinjai dan Pulau Penyalai, pemerintah perlu memastikan komitmen dan pendanaan maintenance untuk PLTS terpasang.
Tentu hal itu harus disiapkan pemerintah, jika sumber pendanaan utama dari APBN. Namun, sebenarnya pemerintah punya opsi lain dengan memanfaatkan badan usaha milik desa (BUMDes).
Seperti BUMDes di Muara Enggelam, Kalimantan Timur yang sukses merawat PLTS berkapasitas 42 KW secara komunal sejak 2015. Berkat tata kelola BUMDes yang optimal, mereka bisa menyumbang Rp400 juta untuk pembelian baterai tambahan.
Membangun ekosistem energi terbarukan
Researcher & Engagement Lead IEEFA, Mutya Yustika, menilai sebelum mengejar kapasitas raksasa, pemerintah seharusnya fokus membangun ekosistem energi terbarukan. Ekosistem yang menggeliat bisa menekan harga PLTS di Indonesia sehingga energi surya lebih terjangkau untuk diakses masyarakat dan desa.
Saat ini ekosistem PLTS Indonesia belum memadai. Tengok saja PT Indonesia Solar Global yang mengaku biaya produksi fotofoltaik mereka 15% lebih mahal ketimbang Cina.
Saat ini harga rata-rata panel surya di Indonesia sekitar US$1 per Watt-peak (Wp), sementara di Cina hanya sekitar US$0,20–0,30 per Wp. Artinya, biaya memasang PLTS di Indonesia bahkan bisa sampai tiga hingga lima kali lipat lebih mahal.
Perbedaan ini terjadi karena ekosistem industri panel surya di dalam negeri belum terbentuk sepenuhnya. Mulai dari rantai pasok komponen, skala produksi, hingga kebijakan yang mendorong permintaan pasar.
Secara umum, penetrasi energi terbarukan juga masih sulit karena pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang masih mendominasi sumber listrik di Indonesia. Apalagi hampir seluruh subsidi diarahkan ke energi fosil sehingga energi terbarukan –yang menerima jauh lebih sedikit subsidi– justru terhambat. Ini menjadi masalah yang seharusnya diatasi pemerintah ketimbang langsung melimpahkan beban ekspansi energi terbarukan ke desa.
Pentingnya partisipasi dalam perencanaan
Jika proyek energi seperti Satu Desa Satu PLTS dijalankan tanpa melibatkan dan mendengarkan aspirasi masyarakat desa, risikonya justru besar. Proyek bisa berhenti di tengah jalan atau bahkan mangkrak.
Banyak contoh menunjukkan bahwa ketika warga tidak merasa memiliki, mereka enggan terlibat dalam perawatan maupun pengelolaan. Padahal, keberhasilan proyek energi terbarukan di tingkat lokal tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada rasa kepemilikan dan partisipasi masyarakat.
Dengan melibatkan warga sejak tahap perencanaan, desa tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga penjaga keberlanjutan energi terbarukan di wilayahnya.





