Komitmen Iklim SNDC Indonesia 2025: Perbedaan dan Kontroversi
Sita Mellia • Penulis
06 November 2025
307
• 5 Menit membaca
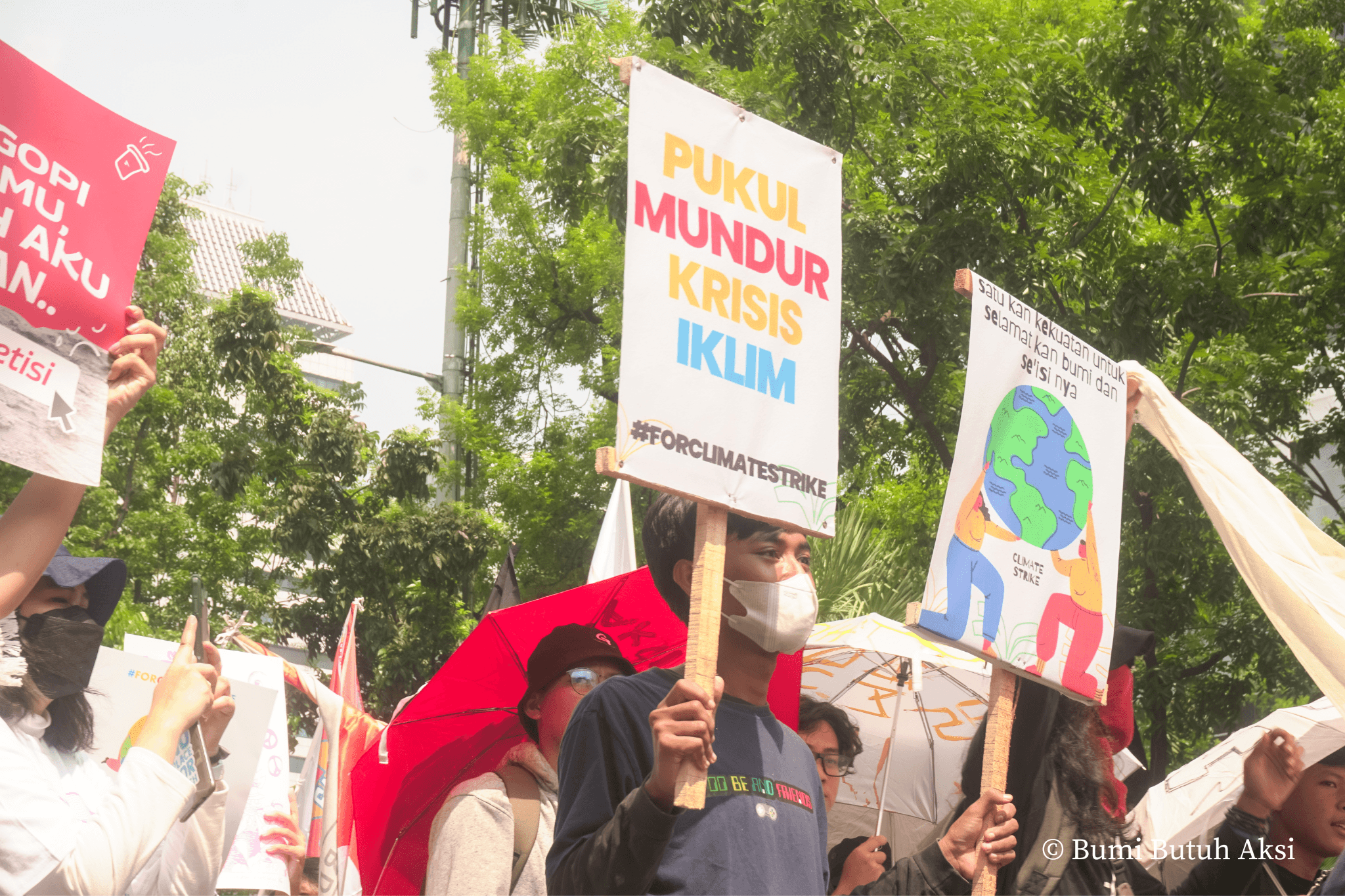
Indonesia akhirnya menyerahkan komitmen iklimnya yang kelima atau Second Nationally Determined Contributions (SNDC) kepada PBB pada 27 Oktober 2025. Rencana aksi iklim dalam SNDC akan disampaikan delegasi dari Indonesia—Hashim Djojohadikusumo—pada Conference of the Parties 30 (COP30) atau Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 pada 10-21 November 2025 di Belém, Brasil.
Dokumen ini menjadi revisi atas Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC). Dalam ENDC, target penurunan emisi dinaikkan menjadi 31.89% (tanpa syarat) dan 43.20% (bersyarat). Sementara itu, narasi ‘net zero emission (NZE)’ atau target emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat pun diperkenalkan tanpa peta jalan yang jelas.
Sayangnya, dokumen penting SNDC ini belum mencerminkan keadilan dan solusi konkret untuk mengurangi emisi, khususnya pada sektor energi yang menyumbang emisi terbesar.
Apa yang berbeda dari SNDC 2025?
Ada beberapa perbedaan antara SNDC dengan ENDC.
Pertama, pengurangan emisi dalam SNDC berbasiskan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) pada 2019 yakni 1.145.037 Gg CO2e, menggantikan skenario acuan Business as Usual (BAU) semula dengan tahun dasar 2010. Emisi ini disumbang oleh lima sektor yaitu energi, IPPU (Industrial Process and Production Use), limbah, pertanian, dan FOLU (Forest and other Land Use).
Kedua, SNDC memperpanjang periode implementasi hingga 2035 dengan dua skenario pertumbuhan ekonomi. Kali ini, SNDC memunculkan skenario Low Carbon Compatible with Paris Low (LCCP_L) dan High (LCCP_H) yang selaras dengan jalur 1,5°C dan dokumen Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR). Dokumen ini menjadi panduan Indonesia menuju NZE menggantikan skenario CM1 (tanpa syarat) dan CM2 (bersyarat) yang sebelumnya termuat dalam ENDC.
Dalam SNDC, skenario pertama dibuat dengan asumsi jika pertumbuhan ekonomi melambat (LCCP_L), maka emisi gas rumah kaca maksimal yang dihasilkan pada 2030 ialah 1,345 gigaton CO2e. Penurunan emisi dalam skenario LCCP_H ditargetkan ke angka 1,257 gigaton CO2e pada 2035.
Sementara skenario kedua ialah jika pertumbuhan ekonomi lebih cepat (LCCP_H), maka emisi gas rumah kaca maksimal yang dihasilkan di tahun 2030 ialah 1,491 gigaton CO2e. Sementara pada 2035, emisi ditargetkan turun menjadi 1,488 gigaton CO2e.
Ketiga, ada perubahan target dimana bentuk target SNDC berupa tingkat emisi absolut di tahun 2030 dan 2035, berbeda dengan target sebelumnya dalam bentuk persentase penurunan emisi tahun 2030 dibandingkan dengan skenario Business as Usual (BAU).
Keempat, SNDC menambah jenis gas rumah kaca yang akan dikurangi. Mulai saat ini, gas rumah kaca yang dikategorikan sebagai pemerangkap panas di atmosfer diperluas menjadi empat yakni CO2 (karbon dioksida), CH4 (metana), N2O (nitrogen dioksida), and HFCs (hidrofluorokarbon).
Kelima, SNDC memiliki basis kebijakan yang mengintegrasikan regulasi baru seperti PP No. 33/2023 (Konservasi Energi), PP No. 26/2025 (Perencanaan Lingkungan), dan KepmenLH No. 842/2024 (Zero Waste-Zero Emission).
Keenam, dalam langkah adaptasi terhadap krisis iklim, SNDC mempertimbangkan beberapa sektor. Diantaranya ialah pangan, air, energi, kesehatan, ekosistem, dan bencana serta co-benefits dengan aksi mitigasi.
Target tak realistis, solusi palsu, dan minim partisipasi publik
Tak berbeda dengan NDC sebelumnya, dokumen terbaru ini pun masih menyisakan banyak pertanyaan: seberapa kuat komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi secara signifikan dan berkeadilan, bukan sekadar kesepakatan politik dan ekonomi yang menguntungkan segelintir orang?
Dalam SNDC yang dikeluarkan pada 2025, Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan emisi dengan angka yang tak realistis. SNDC memiliki target penurunan emisi ke angka 1,257 juta hingga 1,488 juta MtCO₂ pada 2035.
Padahal, analisis Climate Action Tracker pada 2025 menyebut, emisi Indonesia idealnya sekitar 580 MtCO₂e pada 2035 jika ingin menahan laju suhu di bawah 1.5°C.
SNDC Indonesia masih menempatkan sektor kehutanan dan lahan sebagai tumpuan utama mitigasi, sebab pemerintah masih menganggap FOLU adalah sumber emisi terbesar.
Ini sangat disayangkan sebab sektor energi lah yang menjadi penyumbang emisi terbesar secara nasional akibat ketergantungan terhadap batu bara dan pembangunan PLTU captive di kawasan industri nikel.
Komitmen untuk mewujudkan transisi energi yang berkeadilan juga masih bersifat normatif, tak ada langkah konkret seperti penutupan PLTU atau penghentian insentif dan subsidi untuk energi fosil. Padahal, Climate Action Tracker pun sudah mengingatkan bahwa Indonesia perlu berkomitmen untuk menutup PLTU batu bara secara bertahap pada 2040, sejalan dengan Perjanjian Paris dan selaras dengan Peraturan Menteri ESDM No. 10/2025.
Berbagai solusi palsu dalam transisi energi juga masih ditemukan dalam SNDC Indonesia. Pada sektor energi, SNDC masih mengandalkan biofuel yakni biodiesel untuk mengurangi emisi dari transportasi. Berbagai studi telah menilai biodiesel akan memperparah emisi, menambah masalah sosial-ekologis baru, dan merugikan petani lokal. Selain biodiesel, SNDC masih menjadikan gas fosil sebagai langkah transisi energi. Padahal, gas fosil justru lebih berbahaya sebab lebih kuat memerangkap panas di atmosfer karena melepas gas metana.
Dari sisi pendanaan iklim, SNDC 2025 membutuhkan total investasi sebesar Rp7.552,5 triliun (US$ 472,6 miliar) untuk mencapai target iklimnya. Dokumen ini menyebut perlunya kolaborasi antara publik, swasta, dan lembaga internasional melalui skema blended finance.
Sayangnya, SNDC tidak menjelaskan bagaimana investasi tersebut akan diarahkan secara adil dan menyentuh kelompok rentan yang paling terdampak krisis iklim. Misalnya, untuk memastikan perlindungan terhadap masyarakat pesisir yang terdampak kenaikan permukaan air laut seperti nelayan atau memberikan peta jalan transisi pekerja PLTU ke pekerjaan hijau. Angka yang akan mengatasi emisi dari empat sektor—energi, pertanian, FOLU, dan limbah—ini pun tak jelas sektor apa yang akan menjadi prioritas serapan pendanaan.
Dokumen SNDC yang diserahkan terlambat—delapan bulan lebih lama dari deadline—serta ditunggu-tunggu masyarakat sejak era pemerintahan Joko Widodo ini pun masih jauh dari keadilan. Pemerintah tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan SNDC. Sebelum Kementerian Lingkungan Hidup mengadakan konsultasi publik untuk SNDC pada 23 Oktober 2025 lalu, masyarakat sipil kesulitan mengakses draft SNDC.
Pada saat konsultasi berjalan pun lebih terlihat sebagai agenda sosialisasi, bukan konsultasi publik. Penyusunan yang bersifat tertutup ini pada akhirnya melemahkan legitimasi komitmen transisi energi berkeadilan yang ada pada SNDC.





