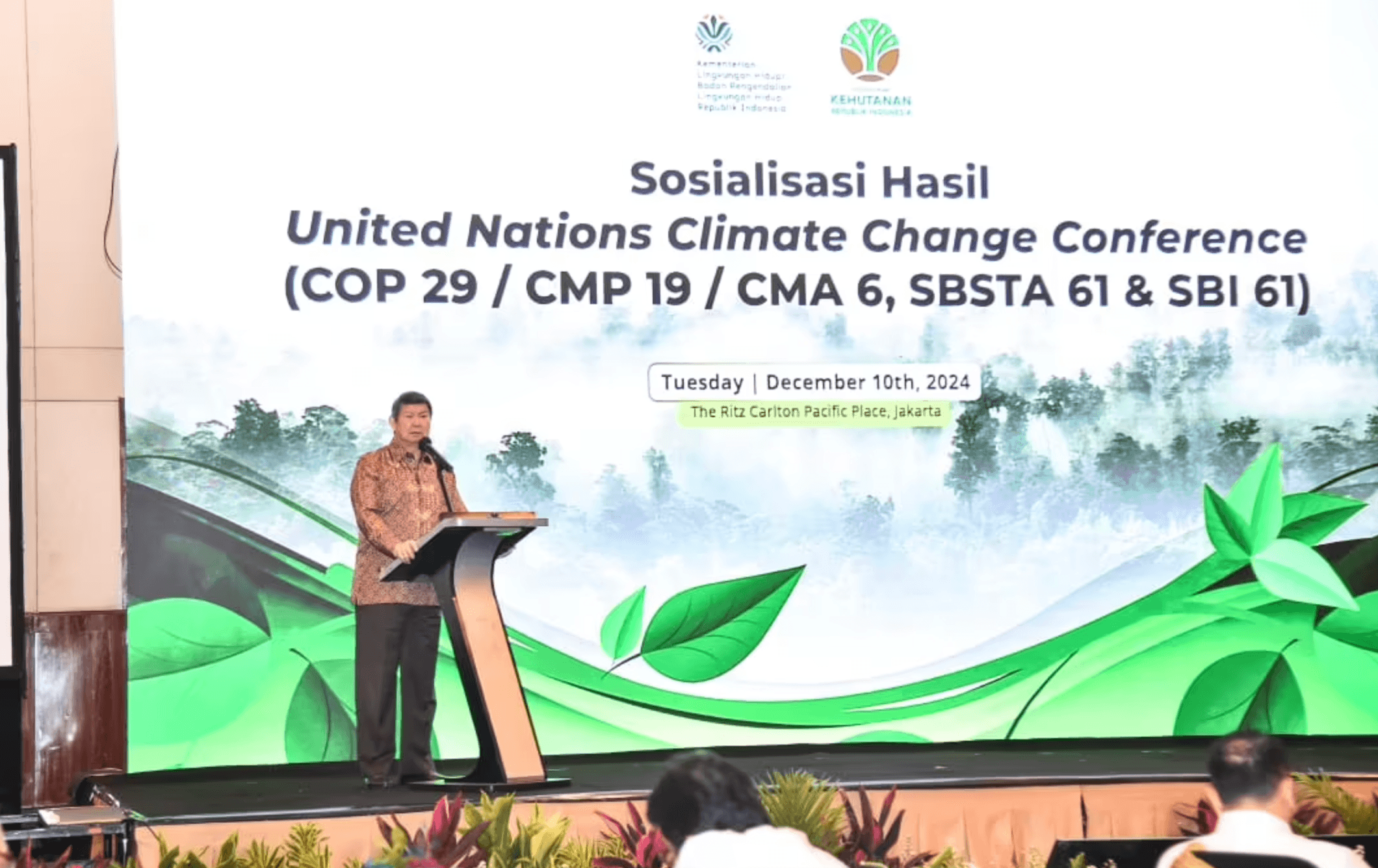Timpangnya Akses PLTS Atap: Mendobrak Elitisme Energi Surya
Sita Mellia • Penulis
12 Agustus 2025
80
• 7 Menit membaca

Indonesia berpeluang besar mendongkrak akses listrik sekaligus menjaga udara bersih dengan memaksimalkan pemasangan PLTS (pembangkit listrik tenaga surya) atap. Potensi PLTS atap Indonesia tercatat sebesar 32,5 gigawatt (GW).
Sayangnya, per Maret 2025, jumlah pelanggan PLTS atap baru menyentuh 10.437 orang. Dari target 3,6 gigawatt peak (GWp) di 2025, kapasitas PLTS atap pun baru terealisasi sebesar 406,78 megawatt peak (MWp).
Ketimpangan ini terjadi karena PLTS atap hanya bisa diakses sebagian kecil warga. Tingginya biaya instalasi panel surya membuat mayoritas PLTS atap hanya bisa diakses oleh perumahan kelas menengah ke atas.
Selain harganya yang mahal, berbagai kebijakan juga belum berpihak pada warga yang belum teraliri listrik di daerah terpencil. Hibah PLTS atap yang beberapa kali dikerahkan belum menyentuh masyarakat di daerah terpencil. Dari target 1.296 pelanggan, realisasi penerima hibah hanya mencapai 383 orang pada Desember 2022—atau sekitar 30%.
Jika pemerintah terus mengeluarkan kebijakan yang ‘meng-elite-kan’ PLTS atap, maka Indonesia akan sulit melepas ketergantungan batu bara. Warga pun kesulitan memperoleh udara sehat akibat dominasi PLTU batu bara sebagai sumber energi listrik negara. Pemerintah perlu membulatkan kemauan politik untuk beralih memberikan insentif atau subsidi PLTS atap, ketimbang menghabiskan kas negara untuk mensubsidi listrik dari energi kotor—PLTU batu bara.
Tak berpihak pada rumah tangga
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) selama ini menjadikan energi surya sebagai barang jualan, alih-alih mempermudah akses listrik bersih buat warganya. Hal ini terlihat dari kebijakan yang membuat panel surya menjadi sumber energi elit.
Pertama, warga harus menghadapi regulasi yang rumit serta tidak inklusif. Di dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024 , pemerintah membatasi kuota pemasangan PLTS atap per provinsi setiap lima tahun. Alasannya, PLTS atap belum andal dalam memberikan pasokan listrik yang stabil, sehingga perlu dibatasi.
Revisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 26/2021 tentang PLTS Atap juga meniadakan skema net-metering dengan menghapus skema jual-beli listrik rumah tangga. Alhasil, rumah tangga yang memasang PLTS atap tak bisa lagi menjual atau mengekspor kelebihan listriknya ke PLN.
Pemerintah berdalih kebijakan ekspor-impor listrik rumah tangga akan menyebabkan oversupply atau kelebihan pasokan listrik, terutama di wilayah dengan kelebihan kapasitas seperti Jawa-Bali. Padahal, kelebihan pasokan listrik bisa diatasi dengan modernisasi jaringan.
Penghapusan skema jual-beli listrik ini semakin menghilangkan minat warga untuk memasang PLTS atap. Pasalnya, warga biasanya lebih sering menggunakan listrik di malam hari, dan kelebihan pasokan listrik di siang hari yang tak terpakai akan mubazir dan tetap membebani tagihan listrik.
Imbasnya, warga juga butuh waktu lebih lama balik modal (payback period) dari pembelian sistem PLTS atap. Di tahun yang sama dengan revisi Permen tersebut, biaya pemasangan investasi PLTS atap masih di angka Rp. 33-61 juta—hanya dapat dijangkau oleh kelas menengah atas.
Dalam kurun 2019 hingga 2021, Institute of Essential and Services Reform (IESR) telah melakukan survei di 7 provinsi soal minat warga terhadap PLTS atap. Hasilnya, keekonomian adalah faktor penentu bagi rumah tangga untuk memasang PLTS atap.
Mayoritas warga juga ingin mendapatkan penghematan minimal 50%. Di kalangan masyarakat perkotaan—Jabodetabek— saja, hanya 8% dari 500 rumah tangga yang merasa membutuhkan PLTS atap. Sisanya, warga merasa tidak membutuhkan PLTS atap karena ketidaktahuan, tidak memiliki biaya, serta tidak mengetahui harganya.
Bisa disimpulkan, energi surya selama ini masih elit, baik dari sisi biaya maupun pengetahuan, bahkan di perkotaan.
Menatap tren ‘revolusi atap’
Melihat kenyataan di atas, pemerintah seharusnya tak menunggu kesadaran masyarakat kelas bawah atau menunggu permintaan dari kelas menengah atas. Pemerintah perlu mengubah paradigma pengembangan PLTS atap dari sekadar pemenuhan target kapasitas energi terbarukan, menjadi upaya pengentasan kemiskinan yang ramah lingkungan.
Kita dapat menengok India, negara yang berhasil mencapai bauran energi terbarukan 50%, lima tahun lebih cepat dari target Perjanjian Paris pada 2030. Selama satu dekade terakhir, India terus menerus mengurangi beban tagihan listrik sekaligus menebalkan kantong warganya melalui PLTS atap.
Berbanding terbalik dengan Indonesia—urusan listriknya masih dimonopoli oleh PLN dan negara menghapus sistem net metering—perusahaan listrik di negara-negara bagian di India mau membeli listrik dari warganya.
Harish, salah satu warga India pun bercerita, selama 12 tahun belakangan, tagihan listriknya hampir 0% berkat adanya mekanisme net-metering. Karena bisa menjual sisa listriknya, ia menilai, PLTS atap merupakan investasi jangka panjang. Tabungannya bertambah seiring kenaikan tarif listrik akibat inflasi.
Sebuah studi di tahun 2025 meneliti persepsi 121 warga soal PLTS atap di Gujarat, India. Separuh di antaranya telah memasang PLTS atap. Studi ini menemukan bahwa alasan utama mayoritas warganya memasang PLTS atap ialah agar mengurangi beban tagihan listrik.
India meyakini bahwa energi surya milik semua warga, sehingga pemerintahnya ringan tangan dalam memberikan subsidi. Pada 2024, sebanyak ₹75.021 crore atau setara Rp 139,24 triliun digelontorkan untuk program PM Surya Ghar—perluasan PLTS atap untuk memberdayakan rumah tangga kelas menengah dan kelas bawah. Targetnya, program berkapasitas 30 gigawatt (GW) ini diperuntukan bagi 10 juta rumah tangga dalam waktu tiga tahun.
Program ini dimulai dari pemberian subsidi sebesar 40% hingga 60% kepada rumah tangga untuk kapasitas 2 kW hingga 3 kW—yaitu ₹30.000 atau ±Rp 5.570.000 per kW untuk sistem hingga 2 kW dan ₹78.000 atau ±Rp 14.020.000 per kW untuk 3 kWp atau lebih. Syarat untuk mendapatkan subsidi ini pun mudah, cukup memegang status sebagai warga negara India sekaligus memiliki atap yang memadai untuk dipasang panel surya.
Berkat program yang inklusif ini, tidak heran jika dalam enam bulan pertama, ada sekitar 13 juta pendaftaran dan 1,8 juta aplikasi, yang menghasilkan 385 ribu pemasangan atau setara 1,8 GW kapasitas PLTS atap baru.
Sementara itu, 'revolusi atap' di Inggris—memasang PLTS atap sebanyak-banyaknya untuk transisi energi yang berkelanjutan— juga berhasil menciptakan perubahan. Per Juli 2025, sebanyak kurang lebih 1,5 juta rumah telah terpasang panel surya di atapnya.
Kebijakan-kebijakan yang dibuat Inggris pun tak semata untuk mendongkrak udara bersih, tapi juga menurunkan beban tagihan listrik rumah tangga.
Baru-baru ini, Inggris menginvestasikan £13.2 miliar (setara Rp270 triliun) pada 2025 untuk memodali mandat Future Homes Standard—setiap bangunan rumah baru harus dipasang panel surya di atapnya untuk mengurangi emisi sekaligus beban rumah tangga. Berkat ini, warga Inggris yang berpindah rumah di tahun depan kemungkinan akan langsung memiliki panel surya di atap rumahnya.
Negara Tiga Singa ini pun menggenjot kapasitas PLTS hingga 3 kali lipat pada akhir 2030 untuk mengurangi beban tagihan listrik rumah tangga. Hasilnya, rumah tangga di Inggris rata‑rata menghemat £440 per tahun. Rumah tangga berpenghasilan rendah hanya memiliki tagihan sepersepuluh dari pengeluaran bulanan rumah tangga termiskin.
Bukan beban, tapi alat memerangi ketimpangan
Cerita-cerita di atas menunjukkan bahwa energi surya sejalan dengan berbagai tujuan kebijakan, seperti udara sehat, pengentasan kemiskinan, dan ketahanan energi.
Studi oleh Nijsse et al di tahun 2023 bahkan menemukan, dunia tengah mengalami titik balik atau tipping point ke energi surya lebih cepat dan tak terbendung meskipun tanpa target iklim yang lebih ambisius. Ini menandakan peralihan ke energi surya adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Skala produksi dan permintaan energi surya sudah cukup besar sehingga teknologi ini tumbuh pesat tanpa perlu subsidi atau dorongan kebijakan besar-besaran lagi.
Sementara di Indonesia, pemerintahnya justru keliru karena masih menempatkan masyarakat (terutama pengguna listrik golongan rumah tangga) sebagai lumbung keuntungan PLN. Paradigma ini perlu digeser: dari yang mulanya masyarakat adalah pembeli listrik, beralih ke paradigma bahwa masyarakat adalah aktor dari transisi energi. Dengan begitu, energi matahari—energi milik kita semua yang tak akan pernah habis—mudah diakses warga, alih-alih menjadi barang yang sulit digapai.